Divonis
"Apakah mereka di sini?" Kami memuntahkan kata-kata itu, menyembur seperti air dari paru-paru. Setelah air, hanya pertanyaan inilah yang penting. "Apakah mereka berhasil?"
Wajah Uncle Jeb mustahil dibaca di dalam kegelapan. "Siapa?" tanyanya.
"Jamie, Jared!" Bisikan kami membakar bagai teriakan. "Jared bersama Jamie. Adik kami! Apakah mereka di sini? Apakah mereka datang? Apakah kau juga menemukan mereka?"
Nyaris tak ada Jeda.
"Tidak." Jawaban Uncle Jeb tegas. Tak ada rasa iba di dalam suaranya, sama sekali tak ada emosi.
"Tidak," bisik kami. Kami tidak menirukan Uncle Jeb, tapi memprotes mengapa kami memperoleh hidup kami kembali. Apa gunanya? Kembali kami memejamkan mata dan mendengarkan rasa sakit di tubuh kami. Kami membiarkan perasaan itu mengalahkan rasa sakit di benak kami.
"Dengar," ujar Uncle Jeb setelah beberapa saat. "Aku, uh, aku harus mengurus sesuatu. Istirahatlah sejenak, dan aku akan datang menjemputmu."
Kami tidak memahami makna tersembunyi di dalam kata-katanya, hanya mendengar suaranya. Mata kami tetap terpejam. Langkah Uncle Jeb bergemerisik pelan menjauh. Kami tak tahu ke arah mana ia pergi. Lagi pula kami tak peduli.
Mereka sudah lenyap. Tak ada cara untuk mencari mereka. Tak ada harapan. Jared dan Jamie telah hilang. Mereka sangat ahli melakukan hal itu. Dan kami takkan pernah berjumpa mereka lagi.
Air dan udara malam yang lebih sejuk menyadarkan kami, dan itu sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami berguling, kembali membenamkan wajah di pasir. Kami sangat lelah, melampaui batas kelelahan dan memasuki keadaan yang lebih serius serta menyakitkan. Kami pasti bisa tidur. Yang harus kami lakukan hanya tidak berpikir. Kami sanggup melakukannya.
Dan kami melakukannya.
Ketika kami terbangun, hari masih gelap walaupun fajar sudah mengancam di cakrawala timur. Pegunungan didereti warna merah suram. Mulut kami seperti debu, dan pertama-tama kami yakin kemunculan Uncle Jeb hanya mimpi. Tentu saja kami bermimpi.
Kepala kami lebih jernih pagi ini, dan dengan cepat kami mengamati bentuk aneh di dekat pipi kanan--sesuatu yang bukan batu atau kaktus. Kami menyentuhnya, terasa keras dan licin. Kami menyikutnya, dan muncul suara air yang bergerak-gerak di dalamnya.
Uncle Jeb benar-benar nyata, dan ia meninggalkan wadah air untuk kami.
Kami duduk hati-hati, dan terkejut ketika tubuh kami tidak patah jadi dua seperti ranting kering. Sebenarnya kami merasa lebih baik. Agaknya air itu sempat bekerja melalui beberapa bagian tubuh kami. Rasa sakitnya berkurang. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, kami kembali merasa lapar.
Jari-jari kami kaku dan kikuk ketika memutar tutup wadah air itu. Tidak begitu penuh, tapi cukup banyak air untuk mengembangkan dinding-dinding perut kami lagi. Agaknya perut kami telah menciut. Kami menghabiskan air itu, tak sudi lagi menjatah-jatah.
Kami menjatuhkan wadah air logam itu ke pasir, menciptakan suara gedebuk pelan dalam keheningan menjelang fajar. Kini kami terjaga sepenuhnya. Kami mendesah, karena lebih menyukai ketidaksadaran, lalu membenamkan kepala ke dalam tangan. Sekarang bagaimana?
"Mengapa kau memberinya air, Jeb?" desak sebuah suara marah, persis di belakang punggung kami.
Kami berputar dalam posisi berlutut. Pemandangan yang kami lihat merontokkan jantung dan memecah kesadaran kami.
Delapan manusia berdiri membentuk setengah lingkaran, mengelilingi tempatku berlutut di bawah pohon. Tak perlu dipertanyakan lagi, mereka manusia. Mereka semua. Aku belum pernah melihat wajah-wajah yang nyengir membentuk ekspresi semacam itu--belum pernah kulihat di wajah bangsaku. Bibir-bibir itu menyeringai penuh kebencian, menyingkapkan gigi yang dikertakkan seperti hewan lliar. Alis-alis itu mengerut rendah di atas mata yang terbakar kemarahan.
Enam laki-laki dan dua perempuan. Beberapa di antaranya bertubuh sangat besar, sebagian besar lebih besar dariku. Kurasakan wajahku memucat ketika menyadari mengapa tangan mereka terangkat dengan ganjil. Mereka menggenggam erat-erat sebuah benda di depan tubuh masing-masing. Mereka memegang senjata. Beberapa memegang pisau--beberapa di antaranya pisau pendek seperti yang kusimpan di dapur, beberapa lebih panjang, lalu ada pisau yang besar dan mengancam. Pisau ini tidak berguna di dapur. Melanie memasok namanya untukku: parang.
Manusia lainnya menggenggam batang panjang, sebagian logam, sebagian kayu. Pentungan.
Aku mengenali Uncle Jeb di antara mereka. Kedua tangannya memegang santai benda yang tak pernah kulihat dengan mata kepala sendiri, walaupun ada di dalam ingatan-ingatan Melanie, sama seperti pisau besar tadi. Itu senapan.
Aku melihat kengerian, tapi Melanie melihat semua ini dengan terpukau. Benaknya takjub dengan jumlah mereka. Delapan manusia yang bertahan hidup. Ia mengira Jeb sendirian atau dalam skenario terbaik, hanya ditemani dua manusia lainnya. Hati Melanie diliputi kegembiraan, melihatku betapa banyak bangsanya yang masih hidup.
Kau tolol, ujarku. Lihat mereka. Amati mereka.
Aku memaksa Melanie melihat mereka dari sudut pandangku: melihat bentuk-bentuk mengancam di balik jins kotor dan kemeja katun tipis kecokelatan yang penuh debu. Dulunya mungkin mereka manusia--dalam aarti yang ada di dalam pikiran Melanie. Tapi saat ini mereka sudah berubah. Mereka barbar, monster. Mereka mengancam kami, haus darah.
Tampak hukuman mati dalam setiap pasang mata itu.
Melanie melihat semua ini dan, walaupun bersungut-sungut, ia harus mengakui kebenaran pendapatku. Saat ini manusia-manusia tercintanya berada dalam keadaan terburuk, seperti berita-berita di koran yang kami temukan di gubuk terlantar itu. Kami sedang memandang para pembunuh.
Seharusnya kami lebih bijak; seharusnya kami mati kemarin.
Mengapa Uncle Jeb mempertahankan hidup kami untuk ini?
Aku bergidik memikirkannya. Kutelusuri sejarah-sejarah kekejaman manusia. Aku tak sanggup melihatnya. Mungkin seharusnya aku lebih berkonsentrasi. Aku tahu, ada alasan mengapa manusia membiarkan musuh mereka tetap hidup selama beberapa waktu. Mereka menginginkan beberapa hal dari benak atau tubuh musuh mereka...
Tentu saja aku langsung memikirkan satu-satunya rahasia yang mereka inginkan dariku. Rahasia yang tak akan, takkan pernah, kuceritakan kepada mereka. Tak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Aku harus membunuh diriku sendiri lebih dulu.
Tak kubiarkan Melanie melihat rahasia yang kulindungi itu. Aku menggunakan pertahanan-pertahanan Melanie sendiri untuk melawannya, dengan membangun dinding di kepalaku. Dan aku bersembunyi di baliknya ketika memikirkan informasi itu untuk pertama kali sejak penyisipan. Belum pernah ada alasan untuk memikirkan rahasia itu sebelumnya.
Melanie, yang berada di depan dinding, bahkan nyaris tidak merasa penasaran. Ia tidak mencoba menembus dinding itu. Saat ini kekhawatirannya jauh lebih banyak, jika dibandingkan dengan kenyataan ia bukan satu-satunya yang menyimpan informasi rahasia.
Adakah artinya jika aku melindungi rahasiaku darinya? Aku tidak sekuat Melanie; aku yakin ia bisa menahan siksaan. Seberapa besar rasa sakit yang bisa kutahan, sebelum aku menyerah pada semua keinginan mereka?
Perutku bergolak. Bunuh diri adalah pilihan menjijikkan--dan lebih buruk lagi, itu juga berarti pembunuhan. Melanie akan jadi bagian dari siksaan atau kematian itu. Aku akan menunggu sampai benar-benar tak punya pilihan lain.
Tidak, mereka tak bisa melakukannya. Uncle Jeb takkan pernah membiarkan mereka melukaiku.
Uncle Jeb tidak tahu kau berada di sini, ujarku mengingatkan Melanie.
Katakan padanya!
Aku memusatkan perhatian pada wajah lelaki tua itu. Janggut putih tebalnya tidak memungkinkanku melihat bentuk mulutnya, tapi tampaknya matanya tidak membara seperti yang lain. Dari sudut mata aku bisa melihat beberapa lelaki mengalihkan pandang dariku ke Uncle Jeb. Mereka menunggu jawaban atas pertanyaan yang menyadarkanku akan kehadiran mereka. Uncle jeb menatapku, mengabaikan mereka.
Tak bisa kukatakan kepadanya, Melanie. Ia takkan percaya. Dan jika mereka menganggapku berbohong, mereka akan mengira aku adalah Pencari. Mereka pasti cukup berpengalaman, sehingga hanya tahu Pencari-lah yang akan datang ke sini berbekal kebohongan, berbekal cerita yang dirancang untuk memungkinkan penyusupan.
Melanie langsung memahami kebenaran pikiranku. Bahkan kata Pencari saja membuatnya mengerut ketakutan. Dan ia tahu orang-orang asing ini akan menunjukkan reaksi yang sama.
Lagi pula tak ada gunanya. Aku adalah jiwa--itu cukup bagi mereka.
Satu-satunya manusia yang memegang parang--lelaki terbesar di sana, dengan rambut hitam, kulit putih ganjil, dan mata biru cerah--mengeluarkan suara yang menunjukkan rasa jijik dan meludah ke tanah. Ia melangkah maju, lalu perlahan-lahan mengangkat pisau panjang itu.
Lebih baik cepat daripada pelan-pelan. Lebih baik tangan brutal itu, dan bukan tanganku yang membunuh kami. Lebih baik aku tidak mati sebagai mahluk kejam yang bertanggung jawab atas darah Melanie sekaligus darahku sendiri.
"Tunggu, Kyle." Kata-kata Jeb tidak terburu-buru, nyaris santai, tapi lelaki bertubuh besar itu berhenti. Ia nyengir, lalu berbalik menghadap paman Melanie.
"Kenapa? Katamu kau sudah memastikan. Dia salah satu dari mereka."
Aku mengenali suara itu. Itu orang yang sama yang bertanya kepada Jeb mengapa ia memberiku air.
"Well, ya, itu pasti. Tapi ini agak rumit."
"Bagaimana bisa?" Lelaki lain yang mengucapkkan pertanyaan itu. Ia berdiri di samping Kyle yang bertubuh besar dan berambut gelap. Mereka sangat mirip, sehingga pasti kakak-beradik.
"Dia juga keponakanku."
"Tidak lagi. Bukan lagi," ujar Kyle datar. Ia kembali meludah, dan sengaja maju selangkah ke arahku dengan pisau teracung. Dari bahunya yang condong ke depan bisa kulihat kata-kata takkan bisa lagi menghentikannya. Kupejamkan mata.
Terdengar dua klik logam tajam, dan seseorang terkesiap. Mataku kembali terbuka.
"Kubilang tunggu, Kyle." Suara Uncle Jeb masih santai, tapi kini senapan panjang tergenggam erat di tangannya, moncongnya terarah ke punggung Kyle. Kyle terpaku hanya beberapa langkah dariku, parangnya teracung tak bergerak di udara, di atas bahunya.
"Jeb," ujar saudara laki-laki Kyle ketakutan, "apa maumu?"
"Menjauhlah dari gadis itu, Kyle."
Kyle berbalik memunggungi kami, berputar marah menghadap Jeb. "Itu bukan gadis, Jeb!"
Jeb mengangkat bahu; posisi senapannya masih tak berubah di kedua tangannya, masih mengarah kepada Kyle.
"Ada beberapa hal yang harus dibahas."
"Mungkin si dokter bisa mempelajari sesuatu darinya," ujar suara parau perempuan.
Aku ciut mendengar kata-katanya, mendengar ketakutan terburukku di dalamnya. Ketika Jeb tadi menyebutku keponakannya dengan tolol aku membiarkan sepercik harapan menyala--mungkin akan muncul rasa iba. Aku tolol jika mengira seperti itu, bahkan untuk sedetik saja. Kematian adalah satu-satunya rasa iba yang bisa kuharapkan dari mahluk-mahluk ini.
Kutatap perempuan yang baru saja bicara itu, dan aku terkejut melihat ia sama tuanya dengan Jeb, bahkan mungkin lebih tua. Rambutnya tidak berwarna putih, melainkan abu-abu gelap. Karena itulah aku tidak memperhatikan usianya. Wajahnya penuh keriput, dan semua terlipat membentuk garis-garis kemarahan. Tapi ada sesuatu yang kukenal dari ekspresi wajah itu, di balik garis-garis amarahnya.
Melanie menghubungkan wajah tua ini dengan wajah lain yang lebih halus di dalam ingatannya.
"Aunt Maggie? Kau di sini? Bagaimana bisa? Apakah Sharon--"
Itu semua kata-kata Melanie, tapi mengalir keluar dari mulutku, dan aku tak sanggup menghentikannya. Setelah begitu lama bersama-sama di padang gurun, ia jadi semakin kuat atau aku semakin lemah. Atau mungkin karena aku sedang berkonsentrasi untuk mengetahui dari mana pukulan kematian itu bakal datang. Aku sedang bersiap-siap menghadapi pembunuh kami, tapi Melanie menghadapi reuni keluarga.
Melanie hanya sempat mengucapkan setengah teriakan terkejutnya. Perempuan yang jauh lebih tua bernama Maggie menerjang dengan kecepatan yang mengingkari tubuh rapuhnya. Ia tidak mengangkat tangannya yang memegang linggis hitam. Itu tangan yang sedang kuawasi, jadi aku tidak melihat tangan satunya terayun untuk menampar wajahku keras-keras.
Kepalaku tersentak ke belakang, lalu ke depan. Ia menamparku lagi.
"Kau tidak bisa menipu kami, parasit. Kami tahu cara kerjamu. Kami tahu betapa baik kau bisa menirukan kami."
Kurasakan darah keluar di pipi bagian dalam.
Jangan berbuat seperti itu lagi, ujarku memarahi Melanie. Sudah kubilang apa yang akan mereka pikirkan.
Melanie kelewat terkejut untuk menjawab.
"Wah, Maggie," Jeb memulai, nada suaranya menenangkan.
"Jangan bilang 'Wah, Maggie' kepadaku. Dasar lelaki tua tolol! Parasit itu mungkin memimpin satu legiun bangsanya menuju kemari." Aunt Maggie menjauh dariku, matanya menilai sikap diamku seakan-akan aku ular yang bergelung. Ia berhenti di samping saudara laki-lakinya.
"Aku tidak melihat yang lain," tukas Jeb. "Hei" serunya, dan aku terenyak. Aku bukan satu-satunya. Jeb melambaikan tangan kirinya di atas kepala, senapan masih tergenggam di tangan kanan. "Di sini!"
"Diam," gerutu Maggie. Didorongnya dada Jeb. Walaupun aku sangat yakin dengan kekuatan perempuan tua itu, Jeb tidak goyah.
"Dia sendirian, Mag. Dia bisa dibilang sudah mati ketika aku menemukannya. Sekarang keadaannya juga tidak begitu baik. Kaki seribu tidak akan mengorbankan bangsanya dengan cara seperti ini. Mereka pasti akan datang menolong, jauh lebih cepat daripadaku. Apa pun dia, dia sendirian."
Aku melihat gambaran serangga panjang berkaki banyak di dalam kepalaku, tapi tak bisa melihat hubungannya dengan perkataan Uncle Jeb.
Dia sedang membicarakanmu, Melanie menerjemahkan. Diletakkannya gambaran serangga jelek itu di samping ingatanku mengenai sesosok jiwa berwarna perak cemerlang. Aku tidak melihat adanya kesamaan.
Aku heran dari mana Uncle Jeb tahu seperti apa bentukmu, renung Melanie. Pada awalnya ingatanku mengenai bentuk asli jiwa merupakan pengetahuan baru bagi Melanie.
Aku tak punya waktu untuk merenung bersama Melanie. Jeb menghampiriku, dan yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Tangan Kyle terangkat di dekat bahu Jeb, siap menahan atau menyingkirkannya. Aku tak yakin.
Jeb memindahkan senapan ke tangan kiri, lalu mengulurkan tangan kanannya kepadaku. Aku mengawasinya dengan cemas, menunggu tangan itu memukulku.
"Ayo," desaknya lembut. "Seandainya bisa membawamu sejauh itu, aku akan membawamu pulang semalam. Kau harus berjalan kaki agak jauh."
"Tidak!" gerutu Kyle.
"Aku akan membawanya pulang," kata Jeb, untuk pertama kali aku mendengar nada yang agak keras di dalam suaranya. Di balik janggut itu rahangnya membentuk garis tegas.
"Jeb!" protes Maggie.
"Itu rumahku, Mag. Akan kulakukan apa yang kuinginkan."
"Si tua tolol!" bentak Maggie lagi.
Jeb mengulurkan tangan, meraih tanganku yang terkepal di paha. Ia menarikku berdiri. Bukan dengan kasar, tapi seakan terburu-buru. Tapi bukankah memperpanjang hidupku untuk alasan-alasan yang ia miliki merupakan bentuk kekejaman terparah?
Aku bergoyang-goyang tidak stabil. Kakiku tidak terlalu bisa kurasakan. Yang ada hanya perasaan seperti ditusuk-tusuk jarum keitka darah mengalir turun.
Terdengar desis tidak setuju dari belakang Jeb. Dikeluarkan lebih dari satu mulut.
"Oke, siapapun kau," kata Jeb kepadaku, suaranya tetap ramah. "Ayo, pergi dari sini sebelum udara memanas."
Lelaki yang agaknya saudara laki-laki Kyle itu menyentuh lengan jeb.
"Kau tidak boleh menunjukkan tempat tinggal kita, Jeb."
"Kurasa itu tak masalah," ujar Maggie kasar. "Dia tidak akan punya peluang untuk bercerita."
Jeb mendesah. Dari leher ia menarik bandana yang tersembunyi di balik janggut.
"Ini konyol," gumamnya. Tapi ia menggulung kain kotor yang kaku oleh keringat kering itu menjadi penutup mata.
Aku tetap diam ketika Jeb mengikatkan kain itu menutupi mataku. Kuperangi rasa panik yang semakin meningkat karena aku tak bisa melihat musuh-musuhku.
Aku tak bisa melihat, tapi tahu Jeb meletakkan sebelah tangannya di punggungku dan menuntunku; tak satu un dari mereka bisa bersikap begitu lembut.
Kami mulai berjalan, kurasa menuju utara. Mula-mula tak seorang pun bicara--yang terdengar hanya suara pasir tergilas di bawah banyak kaki. Tanahnya rata, tapi aku terus-menerus tersandung kakiku sendiri yang mati rasa. Jeb bersikap sabar; tangannya menuntunku nyaris bisa dikatakan sangat kesatria.
Kurasakan terbitnya matahari ketika kami berjalan. Beberapa langkah kaki terdengar lebih cepat daripada lainnya. Mereka bergerak di depan kami, sehingga sulit didengar. Tampaknya seolah-olah hanya sebagian kecil yang tetap tinggal bersamaku dan Jeb. Agaknya aku tidak kelihatan memerlukan banyak pengawal--tubuhku lemah akibat kelaparan, dan aku terhuyung-huyung di setiap langkah; kepalaku pening dan kosong.
"Kau tidak berencana untuk bercerita kepadanya, bukan?"
Itu suara Maggie; beberapa puluh sentimeter di belakangku, dan kedengarannya seperti menuduh.
"Dia berhak tahu," jawab Jeb. Nada keras kepala itu kembali terdengar di dalam suaranya.
"Perbuatanmu kejam, Jebediah."
"Hidup memang kejam, Maggie."
Sulit untuk memutuskan siapa yang lebih menakutkan di antara keduanya. Apakah Jeb, yang tampak begitu ngotot ingin mempertahankan hidupku? Atau Maggie, yang pertama kali menyarankan dokter, sebutan yang memenuhiku dengan ketakutan yang bersifat naluriah dan memualkan? Tapi perempuan tua itu tampaknya lebih mengkhawatirkan soal kekejaman daripada saudara laki-lakinya.
Selama beberapa jam kami kembali berjalan dalam keheningan. Ketika kakiku roboh, Jeb mendudukkanku di tanah dan mendekatkan tempat air ke bibirku, seperti yang dilakukannya malam itu.
"Beritahu jika kau sudah siap," ujar Jeb. Suaranya ramah, walaupun aku tahu itu interpretasi keliru.
"Kenapa kau berbuat seperti ini, Jeb?" tanya seorang lelaki. Aku pernah mendengar suara itu sebelumnya; salah satu kakak-beradik itu. "Demi Doc? Seharusnya kau bisa bilang begitu kepada Kyle. Tak perlu menodong dengan senapan."
"Kyle perlu lebih sering ditodong senapan," gumam Jeb.
"Katakan kalau ini bukan masalah simpati," lanjut lelaki itu,
"Setelah semua yang kausaksikan..."
"Setelah semua yang kausaksikan, jika aku belum belajar soal belas kasih, diriku takkan banyak berarti. Tapi tidak, ini bukan masalah simpati. Seandainya aku punya cukup banyak simpati untuk mahluk malang ini, aku pasti sudah membiarkannya mati."
Aku menggigil dalam udara sepanas oven.
"Lalu apa?" desak saudara laki-laki Kyle.
Hening panjang, lalu Jeb menyentuh tanganku. Aku meraihnya. Aku perlu pertolongan untuk kembali berdiri. Tangan Jeb yang satu menekan punggungku, dan aku mulai berjalan lagi.
"Rasa penasaran," ujar Jeb pelan.
Tak seorang pun menjawab.
Ketika kami berjalan, aku merenungkan beberapa fakta yang sudah pasti. Satu, aku bukan jiwa pertama yang mereka tangkap. Sudah ada serangkaian rutinitas di sini. "Doc" pernah mencoba memperoleh jawaban dari jiwa-jiwa lain sebelum aku.
Dua, Doc belum berhasil. Seandainya ada jiwa yang batal bunuh diri dan menyerah di bawah siksaan manusia, mereka takkan memerlukanku sekarang. Kematianku bakal cepat dan menyenangkan.
Tapi anehnya aku tak bisa memaksa diri untuk mengharapkan kematian cepat, atau mencoba mewujudkannya. Mudah untuk bunuh diri, bahkan tanpa harus melakukannya sendiri. Yang harus kulakukan hanya menceritakan kebohongan--berpura-pura aku Pencari, mengatakan saat ini rekan-rekanku sedang mencariku, serta membuat da mengancam. Atau mengatakan yang sebenarnya--bahwa Melanie tetap hidup di dalam diriku, dan dialah yang membawaku kemari.
Lalu mereka akan melihat kebohongan lain, kebohongan yang sangat tidak tertanggungkan--gagasan bahwa manusia bisa tetap hidup setelah penyisipan. Gagasan ini begitu menggoda untuk dipercaya dari sudut pandang mereka, begitu licik, sehingga mereka akan semakin yakin aku Pencari, melebihi perkataanku sendiri. Mereka akan menganggap gagasan itu jebakan, menyingkirkanku dengan cepat, lalu mencari tempat lain untuk bersembunyi, jauh dari sini.
Mungkin kau benar, Melanie mengiyakan. Itulah yang akan kulakukan.
Tapi aku belum merasa kesakitan, sehingga sulit bagiku untuk memilih bentuk bunuh diri mana pun; naluriku untuk bertahan hidup membungkam mulutku. Ingatan mengenai pertemuan terakhir dengan Penghibur-ku--saat yang begitu beradab, sehingga tampaknya terjadi di planet lain--berkelebat di kepalaku. Saat itu Melanie menantangku untuk menyingkirkan dirinya. Itu dorongan yang tampaknya bersifat bunuh diri. Tapi ia hanya menggertak. Aku ingat diriku berpikir betapa sulit merenungkan kematian dari kursi yang nyaman.
Semalam aku dan Melanie menginginkan kematian, tapi saat itu kematian hanya beberapa senti jauhnya. Kini setelah aku kembali berdiri di atas kakiku sendiri, rasanya berbeda.
Aku juga tidak ingin mati, bisik Melanie. Tapi mungkin kau keliru, mungkin bukan itu alasan mereka mempertahankan hidup kita. Aku tidak mengerti mengapa mereka... Ia tidak ingin membayangkan hal-hal yang mungkin akan mereka lakukan kepada kami, dan aku yakin bayangan Melanie jauh lebih buruk daripada bayanganku sendiri. Jawaban apa yang teramat sangat mereka inginkan darimu?
Pertanyaan yang berani. Tapi aku memang belum merasa kesakitan...
Satu jam lagi berlalu--matahari tepat di atas kepala, panasnya bagai mahkota api di rambutku--ketika suara yang kudengar berubah. Langkah kaki menggerus pasir nyaris tak bisa lagi kudengar, berubah menjadi gema-gema di depanku. Kaki Jeb masih menggerus pasir seperti kakiku, tapi seseorang di depan kami telah mencapai tempat lain.
"Sekarang hati-hati," Jeb mengingatkan. "Awas, kepalamu."
Aku bimbang, tak yakin apa yang harus kuawasi, atau bagaimana cara mengawasinya dengan mata terpejam. Tangan Jeb meningggalkan punggungku dan menekan kepalaku, menyuruhku menunduk. Aku membungkuk. Leherku kaku.
Jeb menuntunku maju lagi, dan aku mendengar langkah-langkah kami menciptakan bunyi menggema yang sama. Tanahnya tidak terkuak seperti pasir, tidak goyah seperti batu. Melainkan padat dan datar di bawah kakiku.
Matahari lenyap--aku tak bisa lagi merasakan cahayanya membakar kulit atau menghanguskan rambutku.
Aku maju selangkah lagi, dan udara baru menyentuh wajahku. Bukan angin sepoi-sepoi. Ini udara diam-dan aku bergerak memasukinya. Angin padang gurun kering itu lenyap. Udara tak bergerak dan lebih sejuk. Terasa sedikit kelembaban di dalamnya, bau apak yang bisa kucium dan kurasakan.
Muncul begitu banyak pertanyaan di benakku, juga di benak Melanie. ia ingin menyuarakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi aku diam saja. Kini tak satu pun perkataannya ataupun perkataanku bisa membantu kami.
"Oke, kau bisa menegakkan tubuh," ujar Jeb.
Aku mengangkat kepala perlahan-lahan.
Bahkan dengan penutup mata, bisa kukatakan tak ada cahaya. Benar-benar gelap di sekeliling tepi bandana. Aku bisa mendengar yang lain di belakangku menyeret kaki tidak sabar, menungguku bergerak maju.
"Lewat sini," kata Jeb kembali menuntunku. Langkah kami menggema di dekat kami--agaknya ruangan tempat kami berada cukup kecil. Aku mendapati diriku otomatis menunduk.
Kami maju beberapa langkah, lalu mengitari lengkungan tajam yang sepertinya mengembalikan kami ke tempat kedatangan kami. Tanahnya mulai miring ke bawah. Sudutnya semakin curam bersama setiap langkah, dan Jeb mengulurkan tangan kasarnya agar aku tidak jatuh. Aku tak tahu berapa lama aku terselip dan tergelincir melewati kegelapan. Perjalanan itu mungkin terasa lebih panjang daripada sesungguhnya, karena setiap menit diperlambat oleh kengerianku.
Kami kembali berbelok, lalu lantai mulai menanjak. Kakiku begitu mati rasa dan kaku sehingga ketika jalurnya semakin curam, Jeb harus setengah menyeretku ke atas. Semakin jauh kami berjalan, udara semakin apak dan lembap, tapi kegelapan tidak berubah. Yang terdengar hanya langkah kami dan gema-gemanya yang dekat.
Jalur itu berubah mendatar dan mulai berliku-liku seperti ular. Akhirnya. Akhirnya cahaya muncul di sekeliling bagian atas dan bawah penutup mataku. Aku berharap penutup itu bergeser, karena aku terlalu takut untuk membukanya sendiri. Tampaknya takkan begitu menakutkan jika aku bisa melihat di mana aku berada dan siapa yang bersamaku.
Bersamaan dengan cahaya, terdengar suara. Suara itu aneh, gumaman percakapan pelan. Kedengarannya nyaris seperti suara air terjun.
Gumam percakapan itu terdengar semakin keras ketika kami bergerak maju. Dan ketika kami semakin dekat, semakin tak terdengar seperti air. Terlalu bervariasi, nada-nada tinggi-rendah bercampur dan bergema. Seandainya tidak begitu sumbang pasti kedengarannya seperti versi buruk musik konstan yang kudengar dan kunyanyikan di Singing World. Kegelapan penutup matanya cocok dengan ingatan itu; ingatan mengenai kebutaan.
Melanie memahami keriuhan itu lebih dulu. Aku tak pernah mendengar suara semacam itu, karena tak pernah bersama-sama manusia sebelumnya.
Itu perselisihan, Melanie tersadar. Kedengarannya begitu banyak orang sedang berselisih.
Ia tertarik dengan suara itu. Kalau begitu, apakah ada lebih banyak manusia lagi di sini? Bahkan jumlah delapan orang pun telah mengejutkan kami. Tempat apakah ini?
Tangan-tangan menyentuh tengkukku, dan aku menjauhi mereka.
"Tenang," kata Jeb. Ditariknya penutup mata dari mataku.
Aku mengerjap perlahan-lahan, dan bayang-bayang di sekelilingku berubah jadi bentuk-bentuk yang bisa kupahami: dinding-dinding kasar dan tidak rata; langit-langit penuh lubang; lantai usang berdebu. Kami di bawah tanah, di suatu tempat, di dalam gua yang terbentuk alami. Tak mungkin kami berada sedalam itu. Kurasa perjalanan kami ke atas lebih panjang daripada perjalanan kami ke bawah.
Dinding dan langit-langit batu itu berwarna cokelat keunguan gelap dan dipenuhi lubang dangkal seperti keju Swiss. Pinggiran lubang - lubang yang letaknya di sebelah bawah lebih tumpul, tapi lingkaran-lingkaran di atas kepalaku lebih tegas dan pinggirannya tampak tajam.
Cahaya datang dari lubang bulat di depan kami. Bentuk lubang itu tidak seperti lubang - lubang yang memenuhi gua, tapi lebih besar. Ini pintu masuk, ambang pintu ke tempat yang lebih terang. Melanie bersemangat, terpukau oleh konsep ada lebih banyak manusia. Aku menahan diri, mendadak khawatir kebutaan mungkin lebih baik daripada penglihatan.
Jeb mendesah. "Maaf," gumamnya, sangat pelan sehingga aku yakin hanya diriku yang mendengarnya.
Aku mencoba menelan ludah, tapi tak bisa. Kepalaku mulai berputar, tapi itu mungkin karena lapar. Ketika Jeb mendorongku melewati lubang besar itu, kedua tanganku gemetar seperti dedaunan tertiup angin kencang.
Terowongan itu berakhir di bilik yang sangat luas, sehingga pertama-tama aku tak bisa memahami apa yang disaksikan mataku. Langit-langitnya terlalu terang dan terlalu tinggi--seperti langit buatan. Kucoba melihat apa yang meneranginya, tapi langit-langit itu mengirimkan tembok-tembok cahaya tajam yang menyakiti mata.
Aku berharap percakapan itu terdengar semakin keras, tapi mendadak sangat hening di dalam ruang gua yang besar.
Lantainya suram dibandingkan langit-langit cemerlang yang tinggi di atas sana. Perlu sejenak bagi mataku untuk memahami semua bentuk itu.
Kerumunan. Tak ada kata lain untuk itu. Kerumunan manusia yang berdiam diri tak bergerak, semua menatapku garang, penuh kebencian, sama seperti yang kulihat fajar tadi.
Melanie kelewat terpukau untuk melakukan sesuatu, kecuali menghitung. 10, 15, 20... 25, 26, 27...
Aku tak peduli ada berapa banyak manusia. Aku berusaha mengatakan kepada Melanie betapa tak berartinya hal itu. Tak perlu dua puluh orang untuk membunuhku. Untuk membunuh kami. Aku mencoba membuat Melanie melihat betapa membahayakan posisi kami, tapi saat itu ia tak bisa kuperingatkan lagi. ia terhanyut dalam dunia manusia, yang tak pernah ia impikan keberadaannya di sini.
Seorang lelaki maju dari kerumunan, dan pertama-tama mataku tertuju pada kedua tangannya, mencari senjata. Kedua tangannya terkepal tapi tak ada benda-benda mengancam lainnya. Mataku, yang sedang menyesuaikan diri dengan cahaya menyilaukan itu melihat warna kulit lelaki itu yang terbakar matahari, lalu mengenalinya.
Tercekik harapan mendadak yang membuatku pening, aku mengangkat mata memandang wajahnya.
---
Jual Nugget dan Sosis Sayur

Pemesanan via email : lwati111@gmail.com
The Host - Bab 13
Divonis
"Apakah mereka di sini?" Kami memuntahkan kata-kata itu, menyembur seperti air dari paru-paru. Setelah air, hanya pertanyaan inilah yang penting. "Apakah mereka berhasil?"
Wajah Uncle Jeb mustahil dibaca di dalam kegelapan. "Siapa?" tanyanya.
"Jamie, Jared!" Bisikan kami membakar bagai teriakan. "Jared bersama Jamie. Adik kami! Apakah mereka di sini? Apakah mereka datang? Apakah kau juga menemukan mereka?"
Nyaris tak ada Jeda.
"Tidak." Jawaban Uncle Jeb tegas. Tak ada rasa iba di dalam suaranya, sama sekali tak ada emosi.
"Tidak," bisik kami. Kami tidak menirukan Uncle Jeb, tapi memprotes mengapa kami memperoleh hidup kami kembali. Apa gunanya? Kembali kami memejamkan mata dan mendengarkan rasa sakit di tubuh kami. Kami membiarkan perasaan itu mengalahkan rasa sakit di benak kami.
"Dengar," ujar Uncle Jeb setelah beberapa saat. "Aku, uh, aku harus mengurus sesuatu. Istirahatlah sejenak, dan aku akan datang menjemputmu."
Kami tidak memahami makna tersembunyi di dalam kata-katanya, hanya mendengar suaranya. Mata kami tetap terpejam. Langkah Uncle Jeb bergemerisik pelan menjauh. Kami tak tahu ke arah mana ia pergi. Lagi pula kami tak peduli.
Mereka sudah lenyap. Tak ada cara untuk mencari mereka. Tak ada harapan. Jared dan Jamie telah hilang. Mereka sangat ahli melakukan hal itu. Dan kami takkan pernah berjumpa mereka lagi.
Air dan udara malam yang lebih sejuk menyadarkan kami, dan itu sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami berguling, kembali membenamkan wajah di pasir. Kami sangat lelah, melampaui batas kelelahan dan memasuki keadaan yang lebih serius serta menyakitkan. Kami pasti bisa tidur. Yang harus kami lakukan hanya tidak berpikir. Kami sanggup melakukannya.
Dan kami melakukannya.
Ketika kami terbangun, hari masih gelap walaupun fajar sudah mengancam di cakrawala timur. Pegunungan didereti warna merah suram. Mulut kami seperti debu, dan pertama-tama kami yakin kemunculan Uncle Jeb hanya mimpi. Tentu saja kami bermimpi.
Kepala kami lebih jernih pagi ini, dan dengan cepat kami mengamati bentuk aneh di dekat pipi kanan--sesuatu yang bukan batu atau kaktus. Kami menyentuhnya, terasa keras dan licin. Kami menyikutnya, dan muncul suara air yang bergerak-gerak di dalamnya.
Uncle Jeb benar-benar nyata, dan ia meninggalkan wadah air untuk kami.
Kami duduk hati-hati, dan terkejut ketika tubuh kami tidak patah jadi dua seperti ranting kering. Sebenarnya kami merasa lebih baik. Agaknya air itu sempat bekerja melalui beberapa bagian tubuh kami. Rasa sakitnya berkurang. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, kami kembali merasa lapar.
Jari-jari kami kaku dan kikuk ketika memutar tutup wadah air itu. Tidak begitu penuh, tapi cukup banyak air untuk mengembangkan dinding-dinding perut kami lagi. Agaknya perut kami telah menciut. Kami menghabiskan air itu, tak sudi lagi menjatah-jatah.
Kami menjatuhkan wadah air logam itu ke pasir, menciptakan suara gedebuk pelan dalam keheningan menjelang fajar. Kini kami terjaga sepenuhnya. Kami mendesah, karena lebih menyukai ketidaksadaran, lalu membenamkan kepala ke dalam tangan. Sekarang bagaimana?
"Mengapa kau memberinya air, Jeb?" desak sebuah suara marah, persis di belakang punggung kami.
Kami berputar dalam posisi berlutut. Pemandangan yang kami lihat merontokkan jantung dan memecah kesadaran kami.
Delapan manusia berdiri membentuk setengah lingkaran, mengelilingi tempatku berlutut di bawah pohon. Tak perlu dipertanyakan lagi, mereka manusia. Mereka semua. Aku belum pernah melihat wajah-wajah yang nyengir membentuk ekspresi semacam itu--belum pernah kulihat di wajah bangsaku. Bibir-bibir itu menyeringai penuh kebencian, menyingkapkan gigi yang dikertakkan seperti hewan lliar. Alis-alis itu mengerut rendah di atas mata yang terbakar kemarahan.
Enam laki-laki dan dua perempuan. Beberapa di antaranya bertubuh sangat besar, sebagian besar lebih besar dariku. Kurasakan wajahku memucat ketika menyadari mengapa tangan mereka terangkat dengan ganjil. Mereka menggenggam erat-erat sebuah benda di depan tubuh masing-masing. Mereka memegang senjata. Beberapa memegang pisau--beberapa di antaranya pisau pendek seperti yang kusimpan di dapur, beberapa lebih panjang, lalu ada pisau yang besar dan mengancam. Pisau ini tidak berguna di dapur. Melanie memasok namanya untukku: parang.
Manusia lainnya menggenggam batang panjang, sebagian logam, sebagian kayu. Pentungan.
Aku mengenali Uncle Jeb di antara mereka. Kedua tangannya memegang santai benda yang tak pernah kulihat dengan mata kepala sendiri, walaupun ada di dalam ingatan-ingatan Melanie, sama seperti pisau besar tadi. Itu senapan.
Aku melihat kengerian, tapi Melanie melihat semua ini dengan terpukau. Benaknya takjub dengan jumlah mereka. Delapan manusia yang bertahan hidup. Ia mengira Jeb sendirian atau dalam skenario terbaik, hanya ditemani dua manusia lainnya. Hati Melanie diliputi kegembiraan, melihatku betapa banyak bangsanya yang masih hidup.
Kau tolol, ujarku. Lihat mereka. Amati mereka.
Aku memaksa Melanie melihat mereka dari sudut pandangku: melihat bentuk-bentuk mengancam di balik jins kotor dan kemeja katun tipis kecokelatan yang penuh debu. Dulunya mungkin mereka manusia--dalam aarti yang ada di dalam pikiran Melanie. Tapi saat ini mereka sudah berubah. Mereka barbar, monster. Mereka mengancam kami, haus darah.
Tampak hukuman mati dalam setiap pasang mata itu.
Melanie melihat semua ini dan, walaupun bersungut-sungut, ia harus mengakui kebenaran pendapatku. Saat ini manusia-manusia tercintanya berada dalam keadaan terburuk, seperti berita-berita di koran yang kami temukan di gubuk terlantar itu. Kami sedang memandang para pembunuh.
Seharusnya kami lebih bijak; seharusnya kami mati kemarin.
Mengapa Uncle Jeb mempertahankan hidup kami untuk ini?
Aku bergidik memikirkannya. Kutelusuri sejarah-sejarah kekejaman manusia. Aku tak sanggup melihatnya. Mungkin seharusnya aku lebih berkonsentrasi. Aku tahu, ada alasan mengapa manusia membiarkan musuh mereka tetap hidup selama beberapa waktu. Mereka menginginkan beberapa hal dari benak atau tubuh musuh mereka...
Tentu saja aku langsung memikirkan satu-satunya rahasia yang mereka inginkan dariku. Rahasia yang tak akan, takkan pernah, kuceritakan kepada mereka. Tak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Aku harus membunuh diriku sendiri lebih dulu.
Tak kubiarkan Melanie melihat rahasia yang kulindungi itu. Aku menggunakan pertahanan-pertahanan Melanie sendiri untuk melawannya, dengan membangun dinding di kepalaku. Dan aku bersembunyi di baliknya ketika memikirkan informasi itu untuk pertama kali sejak penyisipan. Belum pernah ada alasan untuk memikirkan rahasia itu sebelumnya.
Melanie, yang berada di depan dinding, bahkan nyaris tidak merasa penasaran. Ia tidak mencoba menembus dinding itu. Saat ini kekhawatirannya jauh lebih banyak, jika dibandingkan dengan kenyataan ia bukan satu-satunya yang menyimpan informasi rahasia.
Adakah artinya jika aku melindungi rahasiaku darinya? Aku tidak sekuat Melanie; aku yakin ia bisa menahan siksaan. Seberapa besar rasa sakit yang bisa kutahan, sebelum aku menyerah pada semua keinginan mereka?
Perutku bergolak. Bunuh diri adalah pilihan menjijikkan--dan lebih buruk lagi, itu juga berarti pembunuhan. Melanie akan jadi bagian dari siksaan atau kematian itu. Aku akan menunggu sampai benar-benar tak punya pilihan lain.
Tidak, mereka tak bisa melakukannya. Uncle Jeb takkan pernah membiarkan mereka melukaiku.
Uncle Jeb tidak tahu kau berada di sini, ujarku mengingatkan Melanie.
Katakan padanya!
Aku memusatkan perhatian pada wajah lelaki tua itu. Janggut putih tebalnya tidak memungkinkanku melihat bentuk mulutnya, tapi tampaknya matanya tidak membara seperti yang lain. Dari sudut mata aku bisa melihat beberapa lelaki mengalihkan pandang dariku ke Uncle Jeb. Mereka menunggu jawaban atas pertanyaan yang menyadarkanku akan kehadiran mereka. Uncle jeb menatapku, mengabaikan mereka.
Tak bisa kukatakan kepadanya, Melanie. Ia takkan percaya. Dan jika mereka menganggapku berbohong, mereka akan mengira aku adalah Pencari. Mereka pasti cukup berpengalaman, sehingga hanya tahu Pencari-lah yang akan datang ke sini berbekal kebohongan, berbekal cerita yang dirancang untuk memungkinkan penyusupan.
Melanie langsung memahami kebenaran pikiranku. Bahkan kata Pencari saja membuatnya mengerut ketakutan. Dan ia tahu orang-orang asing ini akan menunjukkan reaksi yang sama.
Lagi pula tak ada gunanya. Aku adalah jiwa--itu cukup bagi mereka.
Satu-satunya manusia yang memegang parang--lelaki terbesar di sana, dengan rambut hitam, kulit putih ganjil, dan mata biru cerah--mengeluarkan suara yang menunjukkan rasa jijik dan meludah ke tanah. Ia melangkah maju, lalu perlahan-lahan mengangkat pisau panjang itu.
Lebih baik cepat daripada pelan-pelan. Lebih baik tangan brutal itu, dan bukan tanganku yang membunuh kami. Lebih baik aku tidak mati sebagai mahluk kejam yang bertanggung jawab atas darah Melanie sekaligus darahku sendiri.
"Tunggu, Kyle." Kata-kata Jeb tidak terburu-buru, nyaris santai, tapi lelaki bertubuh besar itu berhenti. Ia nyengir, lalu berbalik menghadap paman Melanie.
"Kenapa? Katamu kau sudah memastikan. Dia salah satu dari mereka."
Aku mengenali suara itu. Itu orang yang sama yang bertanya kepada Jeb mengapa ia memberiku air.
"Well, ya, itu pasti. Tapi ini agak rumit."
"Bagaimana bisa?" Lelaki lain yang mengucapkkan pertanyaan itu. Ia berdiri di samping Kyle yang bertubuh besar dan berambut gelap. Mereka sangat mirip, sehingga pasti kakak-beradik.
"Dia juga keponakanku."
"Tidak lagi. Bukan lagi," ujar Kyle datar. Ia kembali meludah, dan sengaja maju selangkah ke arahku dengan pisau teracung. Dari bahunya yang condong ke depan bisa kulihat kata-kata takkan bisa lagi menghentikannya. Kupejamkan mata.
Terdengar dua klik logam tajam, dan seseorang terkesiap. Mataku kembali terbuka.
"Kubilang tunggu, Kyle." Suara Uncle Jeb masih santai, tapi kini senapan panjang tergenggam erat di tangannya, moncongnya terarah ke punggung Kyle. Kyle terpaku hanya beberapa langkah dariku, parangnya teracung tak bergerak di udara, di atas bahunya.
"Jeb," ujar saudara laki-laki Kyle ketakutan, "apa maumu?"
"Menjauhlah dari gadis itu, Kyle."
Kyle berbalik memunggungi kami, berputar marah menghadap Jeb. "Itu bukan gadis, Jeb!"
Jeb mengangkat bahu; posisi senapannya masih tak berubah di kedua tangannya, masih mengarah kepada Kyle.
"Ada beberapa hal yang harus dibahas."
"Mungkin si dokter bisa mempelajari sesuatu darinya," ujar suara parau perempuan.
Aku ciut mendengar kata-katanya, mendengar ketakutan terburukku di dalamnya. Ketika Jeb tadi menyebutku keponakannya dengan tolol aku membiarkan sepercik harapan menyala--mungkin akan muncul rasa iba. Aku tolol jika mengira seperti itu, bahkan untuk sedetik saja. Kematian adalah satu-satunya rasa iba yang bisa kuharapkan dari mahluk-mahluk ini.
Kutatap perempuan yang baru saja bicara itu, dan aku terkejut melihat ia sama tuanya dengan Jeb, bahkan mungkin lebih tua. Rambutnya tidak berwarna putih, melainkan abu-abu gelap. Karena itulah aku tidak memperhatikan usianya. Wajahnya penuh keriput, dan semua terlipat membentuk garis-garis kemarahan. Tapi ada sesuatu yang kukenal dari ekspresi wajah itu, di balik garis-garis amarahnya.
Melanie menghubungkan wajah tua ini dengan wajah lain yang lebih halus di dalam ingatannya.
"Aunt Maggie? Kau di sini? Bagaimana bisa? Apakah Sharon--"
Itu semua kata-kata Melanie, tapi mengalir keluar dari mulutku, dan aku tak sanggup menghentikannya. Setelah begitu lama bersama-sama di padang gurun, ia jadi semakin kuat atau aku semakin lemah. Atau mungkin karena aku sedang berkonsentrasi untuk mengetahui dari mana pukulan kematian itu bakal datang. Aku sedang bersiap-siap menghadapi pembunuh kami, tapi Melanie menghadapi reuni keluarga.
Melanie hanya sempat mengucapkan setengah teriakan terkejutnya. Perempuan yang jauh lebih tua bernama Maggie menerjang dengan kecepatan yang mengingkari tubuh rapuhnya. Ia tidak mengangkat tangannya yang memegang linggis hitam. Itu tangan yang sedang kuawasi, jadi aku tidak melihat tangan satunya terayun untuk menampar wajahku keras-keras.
Kepalaku tersentak ke belakang, lalu ke depan. Ia menamparku lagi.
"Kau tidak bisa menipu kami, parasit. Kami tahu cara kerjamu. Kami tahu betapa baik kau bisa menirukan kami."
Kurasakan darah keluar di pipi bagian dalam.
Jangan berbuat seperti itu lagi, ujarku memarahi Melanie. Sudah kubilang apa yang akan mereka pikirkan.
Melanie kelewat terkejut untuk menjawab.
"Wah, Maggie," Jeb memulai, nada suaranya menenangkan.
"Jangan bilang 'Wah, Maggie' kepadaku. Dasar lelaki tua tolol! Parasit itu mungkin memimpin satu legiun bangsanya menuju kemari." Aunt Maggie menjauh dariku, matanya menilai sikap diamku seakan-akan aku ular yang bergelung. Ia berhenti di samping saudara laki-lakinya.
"Aku tidak melihat yang lain," tukas Jeb. "Hei" serunya, dan aku terenyak. Aku bukan satu-satunya. Jeb melambaikan tangan kirinya di atas kepala, senapan masih tergenggam di tangan kanan. "Di sini!"
"Diam," gerutu Maggie. Didorongnya dada Jeb. Walaupun aku sangat yakin dengan kekuatan perempuan tua itu, Jeb tidak goyah.
"Dia sendirian, Mag. Dia bisa dibilang sudah mati ketika aku menemukannya. Sekarang keadaannya juga tidak begitu baik. Kaki seribu tidak akan mengorbankan bangsanya dengan cara seperti ini. Mereka pasti akan datang menolong, jauh lebih cepat daripadaku. Apa pun dia, dia sendirian."
Aku melihat gambaran serangga panjang berkaki banyak di dalam kepalaku, tapi tak bisa melihat hubungannya dengan perkataan Uncle Jeb.
Dia sedang membicarakanmu, Melanie menerjemahkan. Diletakkannya gambaran serangga jelek itu di samping ingatanku mengenai sesosok jiwa berwarna perak cemerlang. Aku tidak melihat adanya kesamaan.
Aku heran dari mana Uncle Jeb tahu seperti apa bentukmu, renung Melanie. Pada awalnya ingatanku mengenai bentuk asli jiwa merupakan pengetahuan baru bagi Melanie.
Aku tak punya waktu untuk merenung bersama Melanie. Jeb menghampiriku, dan yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Tangan Kyle terangkat di dekat bahu Jeb, siap menahan atau menyingkirkannya. Aku tak yakin.
Jeb memindahkan senapan ke tangan kiri, lalu mengulurkan tangan kanannya kepadaku. Aku mengawasinya dengan cemas, menunggu tangan itu memukulku.
"Ayo," desaknya lembut. "Seandainya bisa membawamu sejauh itu, aku akan membawamu pulang semalam. Kau harus berjalan kaki agak jauh."
"Tidak!" gerutu Kyle.
"Aku akan membawanya pulang," kata Jeb, untuk pertama kali aku mendengar nada yang agak keras di dalam suaranya. Di balik janggut itu rahangnya membentuk garis tegas.
"Jeb!" protes Maggie.
"Itu rumahku, Mag. Akan kulakukan apa yang kuinginkan."
"Si tua tolol!" bentak Maggie lagi.
Jeb mengulurkan tangan, meraih tanganku yang terkepal di paha. Ia menarikku berdiri. Bukan dengan kasar, tapi seakan terburu-buru. Tapi bukankah memperpanjang hidupku untuk alasan-alasan yang ia miliki merupakan bentuk kekejaman terparah?
Aku bergoyang-goyang tidak stabil. Kakiku tidak terlalu bisa kurasakan. Yang ada hanya perasaan seperti ditusuk-tusuk jarum keitka darah mengalir turun.
Terdengar desis tidak setuju dari belakang Jeb. Dikeluarkan lebih dari satu mulut.
"Oke, siapapun kau," kata Jeb kepadaku, suaranya tetap ramah. "Ayo, pergi dari sini sebelum udara memanas."
Lelaki yang agaknya saudara laki-laki Kyle itu menyentuh lengan jeb.
"Kau tidak boleh menunjukkan tempat tinggal kita, Jeb."
"Kurasa itu tak masalah," ujar Maggie kasar. "Dia tidak akan punya peluang untuk bercerita."
Jeb mendesah. Dari leher ia menarik bandana yang tersembunyi di balik janggut.
"Ini konyol," gumamnya. Tapi ia menggulung kain kotor yang kaku oleh keringat kering itu menjadi penutup mata.
Aku tetap diam ketika Jeb mengikatkan kain itu menutupi mataku. Kuperangi rasa panik yang semakin meningkat karena aku tak bisa melihat musuh-musuhku.
Aku tak bisa melihat, tapi tahu Jeb meletakkan sebelah tangannya di punggungku dan menuntunku; tak satu un dari mereka bisa bersikap begitu lembut.
Kami mulai berjalan, kurasa menuju utara. Mula-mula tak seorang pun bicara--yang terdengar hanya suara pasir tergilas di bawah banyak kaki. Tanahnya rata, tapi aku terus-menerus tersandung kakiku sendiri yang mati rasa. Jeb bersikap sabar; tangannya menuntunku nyaris bisa dikatakan sangat kesatria.
Kurasakan terbitnya matahari ketika kami berjalan. Beberapa langkah kaki terdengar lebih cepat daripada lainnya. Mereka bergerak di depan kami, sehingga sulit didengar. Tampaknya seolah-olah hanya sebagian kecil yang tetap tinggal bersamaku dan Jeb. Agaknya aku tidak kelihatan memerlukan banyak pengawal--tubuhku lemah akibat kelaparan, dan aku terhuyung-huyung di setiap langkah; kepalaku pening dan kosong.
"Kau tidak berencana untuk bercerita kepadanya, bukan?"
Itu suara Maggie; beberapa puluh sentimeter di belakangku, dan kedengarannya seperti menuduh.
"Dia berhak tahu," jawab Jeb. Nada keras kepala itu kembali terdengar di dalam suaranya.
"Perbuatanmu kejam, Jebediah."
"Hidup memang kejam, Maggie."
Sulit untuk memutuskan siapa yang lebih menakutkan di antara keduanya. Apakah Jeb, yang tampak begitu ngotot ingin mempertahankan hidupku? Atau Maggie, yang pertama kali menyarankan dokter, sebutan yang memenuhiku dengan ketakutan yang bersifat naluriah dan memualkan? Tapi perempuan tua itu tampaknya lebih mengkhawatirkan soal kekejaman daripada saudara laki-lakinya.
Selama beberapa jam kami kembali berjalan dalam keheningan. Ketika kakiku roboh, Jeb mendudukkanku di tanah dan mendekatkan tempat air ke bibirku, seperti yang dilakukannya malam itu.
"Beritahu jika kau sudah siap," ujar Jeb. Suaranya ramah, walaupun aku tahu itu interpretasi keliru.
"Kenapa kau berbuat seperti ini, Jeb?" tanya seorang lelaki. Aku pernah mendengar suara itu sebelumnya; salah satu kakak-beradik itu. "Demi Doc? Seharusnya kau bisa bilang begitu kepada Kyle. Tak perlu menodong dengan senapan."
"Kyle perlu lebih sering ditodong senapan," gumam Jeb.
"Katakan kalau ini bukan masalah simpati," lanjut lelaki itu,
"Setelah semua yang kausaksikan..."
"Setelah semua yang kausaksikan, jika aku belum belajar soal belas kasih, diriku takkan banyak berarti. Tapi tidak, ini bukan masalah simpati. Seandainya aku punya cukup banyak simpati untuk mahluk malang ini, aku pasti sudah membiarkannya mati."
Aku menggigil dalam udara sepanas oven.
"Lalu apa?" desak saudara laki-laki Kyle.
Hening panjang, lalu Jeb menyentuh tanganku. Aku meraihnya. Aku perlu pertolongan untuk kembali berdiri. Tangan Jeb yang satu menekan punggungku, dan aku mulai berjalan lagi.
"Rasa penasaran," ujar Jeb pelan.
Tak seorang pun menjawab.
Ketika kami berjalan, aku merenungkan beberapa fakta yang sudah pasti. Satu, aku bukan jiwa pertama yang mereka tangkap. Sudah ada serangkaian rutinitas di sini. "Doc" pernah mencoba memperoleh jawaban dari jiwa-jiwa lain sebelum aku.
Dua, Doc belum berhasil. Seandainya ada jiwa yang batal bunuh diri dan menyerah di bawah siksaan manusia, mereka takkan memerlukanku sekarang. Kematianku bakal cepat dan menyenangkan.
Tapi anehnya aku tak bisa memaksa diri untuk mengharapkan kematian cepat, atau mencoba mewujudkannya. Mudah untuk bunuh diri, bahkan tanpa harus melakukannya sendiri. Yang harus kulakukan hanya menceritakan kebohongan--berpura-pura aku Pencari, mengatakan saat ini rekan-rekanku sedang mencariku, serta membuat da mengancam. Atau mengatakan yang sebenarnya--bahwa Melanie tetap hidup di dalam diriku, dan dialah yang membawaku kemari.
Lalu mereka akan melihat kebohongan lain, kebohongan yang sangat tidak tertanggungkan--gagasan bahwa manusia bisa tetap hidup setelah penyisipan. Gagasan ini begitu menggoda untuk dipercaya dari sudut pandang mereka, begitu licik, sehingga mereka akan semakin yakin aku Pencari, melebihi perkataanku sendiri. Mereka akan menganggap gagasan itu jebakan, menyingkirkanku dengan cepat, lalu mencari tempat lain untuk bersembunyi, jauh dari sini.
Mungkin kau benar, Melanie mengiyakan. Itulah yang akan kulakukan.
Tapi aku belum merasa kesakitan, sehingga sulit bagiku untuk memilih bentuk bunuh diri mana pun; naluriku untuk bertahan hidup membungkam mulutku. Ingatan mengenai pertemuan terakhir dengan Penghibur-ku--saat yang begitu beradab, sehingga tampaknya terjadi di planet lain--berkelebat di kepalaku. Saat itu Melanie menantangku untuk menyingkirkan dirinya. Itu dorongan yang tampaknya bersifat bunuh diri. Tapi ia hanya menggertak. Aku ingat diriku berpikir betapa sulit merenungkan kematian dari kursi yang nyaman.
Semalam aku dan Melanie menginginkan kematian, tapi saat itu kematian hanya beberapa senti jauhnya. Kini setelah aku kembali berdiri di atas kakiku sendiri, rasanya berbeda.
Aku juga tidak ingin mati, bisik Melanie. Tapi mungkin kau keliru, mungkin bukan itu alasan mereka mempertahankan hidup kita. Aku tidak mengerti mengapa mereka... Ia tidak ingin membayangkan hal-hal yang mungkin akan mereka lakukan kepada kami, dan aku yakin bayangan Melanie jauh lebih buruk daripada bayanganku sendiri. Jawaban apa yang teramat sangat mereka inginkan darimu?
Pertanyaan yang berani. Tapi aku memang belum merasa kesakitan...
Satu jam lagi berlalu--matahari tepat di atas kepala, panasnya bagai mahkota api di rambutku--ketika suara yang kudengar berubah. Langkah kaki menggerus pasir nyaris tak bisa lagi kudengar, berubah menjadi gema-gema di depanku. Kaki Jeb masih menggerus pasir seperti kakiku, tapi seseorang di depan kami telah mencapai tempat lain.
"Sekarang hati-hati," Jeb mengingatkan. "Awas, kepalamu."
Aku bimbang, tak yakin apa yang harus kuawasi, atau bagaimana cara mengawasinya dengan mata terpejam. Tangan Jeb meningggalkan punggungku dan menekan kepalaku, menyuruhku menunduk. Aku membungkuk. Leherku kaku.
Jeb menuntunku maju lagi, dan aku mendengar langkah-langkah kami menciptakan bunyi menggema yang sama. Tanahnya tidak terkuak seperti pasir, tidak goyah seperti batu. Melainkan padat dan datar di bawah kakiku.
Matahari lenyap--aku tak bisa lagi merasakan cahayanya membakar kulit atau menghanguskan rambutku.
Aku maju selangkah lagi, dan udara baru menyentuh wajahku. Bukan angin sepoi-sepoi. Ini udara diam-dan aku bergerak memasukinya. Angin padang gurun kering itu lenyap. Udara tak bergerak dan lebih sejuk. Terasa sedikit kelembaban di dalamnya, bau apak yang bisa kucium dan kurasakan.
Muncul begitu banyak pertanyaan di benakku, juga di benak Melanie. ia ingin menyuarakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi aku diam saja. Kini tak satu pun perkataannya ataupun perkataanku bisa membantu kami.
"Oke, kau bisa menegakkan tubuh," ujar Jeb.
Aku mengangkat kepala perlahan-lahan.
Bahkan dengan penutup mata, bisa kukatakan tak ada cahaya. Benar-benar gelap di sekeliling tepi bandana. Aku bisa mendengar yang lain di belakangku menyeret kaki tidak sabar, menungguku bergerak maju.
"Lewat sini," kata Jeb kembali menuntunku. Langkah kami menggema di dekat kami--agaknya ruangan tempat kami berada cukup kecil. Aku mendapati diriku otomatis menunduk.
Kami maju beberapa langkah, lalu mengitari lengkungan tajam yang sepertinya mengembalikan kami ke tempat kedatangan kami. Tanahnya mulai miring ke bawah. Sudutnya semakin curam bersama setiap langkah, dan Jeb mengulurkan tangan kasarnya agar aku tidak jatuh. Aku tak tahu berapa lama aku terselip dan tergelincir melewati kegelapan. Perjalanan itu mungkin terasa lebih panjang daripada sesungguhnya, karena setiap menit diperlambat oleh kengerianku.
Kami kembali berbelok, lalu lantai mulai menanjak. Kakiku begitu mati rasa dan kaku sehingga ketika jalurnya semakin curam, Jeb harus setengah menyeretku ke atas. Semakin jauh kami berjalan, udara semakin apak dan lembap, tapi kegelapan tidak berubah. Yang terdengar hanya langkah kami dan gema-gemanya yang dekat.
Jalur itu berubah mendatar dan mulai berliku-liku seperti ular. Akhirnya. Akhirnya cahaya muncul di sekeliling bagian atas dan bawah penutup mataku. Aku berharap penutup itu bergeser, karena aku terlalu takut untuk membukanya sendiri. Tampaknya takkan begitu menakutkan jika aku bisa melihat di mana aku berada dan siapa yang bersamaku.
Bersamaan dengan cahaya, terdengar suara. Suara itu aneh, gumaman percakapan pelan. Kedengarannya nyaris seperti suara air terjun.
Gumam percakapan itu terdengar semakin keras ketika kami bergerak maju. Dan ketika kami semakin dekat, semakin tak terdengar seperti air. Terlalu bervariasi, nada-nada tinggi-rendah bercampur dan bergema. Seandainya tidak begitu sumbang pasti kedengarannya seperti versi buruk musik konstan yang kudengar dan kunyanyikan di Singing World. Kegelapan penutup matanya cocok dengan ingatan itu; ingatan mengenai kebutaan.
Melanie memahami keriuhan itu lebih dulu. Aku tak pernah mendengar suara semacam itu, karena tak pernah bersama-sama manusia sebelumnya.
Itu perselisihan, Melanie tersadar. Kedengarannya begitu banyak orang sedang berselisih.
Ia tertarik dengan suara itu. Kalau begitu, apakah ada lebih banyak manusia lagi di sini? Bahkan jumlah delapan orang pun telah mengejutkan kami. Tempat apakah ini?
Tangan-tangan menyentuh tengkukku, dan aku menjauhi mereka.
"Tenang," kata Jeb. Ditariknya penutup mata dari mataku.
Aku mengerjap perlahan-lahan, dan bayang-bayang di sekelilingku berubah jadi bentuk-bentuk yang bisa kupahami: dinding-dinding kasar dan tidak rata; langit-langit penuh lubang; lantai usang berdebu. Kami di bawah tanah, di suatu tempat, di dalam gua yang terbentuk alami. Tak mungkin kami berada sedalam itu. Kurasa perjalanan kami ke atas lebih panjang daripada perjalanan kami ke bawah.
Dinding dan langit-langit batu itu berwarna cokelat keunguan gelap dan dipenuhi lubang dangkal seperti keju Swiss. Pinggiran lubang - lubang yang letaknya di sebelah bawah lebih tumpul, tapi lingkaran-lingkaran di atas kepalaku lebih tegas dan pinggirannya tampak tajam.
Cahaya datang dari lubang bulat di depan kami. Bentuk lubang itu tidak seperti lubang - lubang yang memenuhi gua, tapi lebih besar. Ini pintu masuk, ambang pintu ke tempat yang lebih terang. Melanie bersemangat, terpukau oleh konsep ada lebih banyak manusia. Aku menahan diri, mendadak khawatir kebutaan mungkin lebih baik daripada penglihatan.
Jeb mendesah. "Maaf," gumamnya, sangat pelan sehingga aku yakin hanya diriku yang mendengarnya.
Aku mencoba menelan ludah, tapi tak bisa. Kepalaku mulai berputar, tapi itu mungkin karena lapar. Ketika Jeb mendorongku melewati lubang besar itu, kedua tanganku gemetar seperti dedaunan tertiup angin kencang.
Terowongan itu berakhir di bilik yang sangat luas, sehingga pertama-tama aku tak bisa memahami apa yang disaksikan mataku. Langit-langitnya terlalu terang dan terlalu tinggi--seperti langit buatan. Kucoba melihat apa yang meneranginya, tapi langit-langit itu mengirimkan tembok-tembok cahaya tajam yang menyakiti mata.
Aku berharap percakapan itu terdengar semakin keras, tapi mendadak sangat hening di dalam ruang gua yang besar.
Lantainya suram dibandingkan langit-langit cemerlang yang tinggi di atas sana. Perlu sejenak bagi mataku untuk memahami semua bentuk itu.
Kerumunan. Tak ada kata lain untuk itu. Kerumunan manusia yang berdiam diri tak bergerak, semua menatapku garang, penuh kebencian, sama seperti yang kulihat fajar tadi.
Melanie kelewat terpukau untuk melakukan sesuatu, kecuali menghitung. 10, 15, 20... 25, 26, 27...
Aku tak peduli ada berapa banyak manusia. Aku berusaha mengatakan kepada Melanie betapa tak berartinya hal itu. Tak perlu dua puluh orang untuk membunuhku. Untuk membunuh kami. Aku mencoba membuat Melanie melihat betapa membahayakan posisi kami, tapi saat itu ia tak bisa kuperingatkan lagi. ia terhanyut dalam dunia manusia, yang tak pernah ia impikan keberadaannya di sini.
Seorang lelaki maju dari kerumunan, dan pertama-tama mataku tertuju pada kedua tangannya, mencari senjata. Kedua tangannya terkepal tapi tak ada benda-benda mengancam lainnya. Mataku, yang sedang menyesuaikan diri dengan cahaya menyilaukan itu melihat warna kulit lelaki itu yang terbakar matahari, lalu mengenalinya.
Tercekik harapan mendadak yang membuatku pening, aku mengangkat mata memandang wajahnya.
---
"Apakah mereka di sini?" Kami memuntahkan kata-kata itu, menyembur seperti air dari paru-paru. Setelah air, hanya pertanyaan inilah yang penting. "Apakah mereka berhasil?"
Wajah Uncle Jeb mustahil dibaca di dalam kegelapan. "Siapa?" tanyanya.
"Jamie, Jared!" Bisikan kami membakar bagai teriakan. "Jared bersama Jamie. Adik kami! Apakah mereka di sini? Apakah mereka datang? Apakah kau juga menemukan mereka?"
Nyaris tak ada Jeda.
"Tidak." Jawaban Uncle Jeb tegas. Tak ada rasa iba di dalam suaranya, sama sekali tak ada emosi.
"Tidak," bisik kami. Kami tidak menirukan Uncle Jeb, tapi memprotes mengapa kami memperoleh hidup kami kembali. Apa gunanya? Kembali kami memejamkan mata dan mendengarkan rasa sakit di tubuh kami. Kami membiarkan perasaan itu mengalahkan rasa sakit di benak kami.
"Dengar," ujar Uncle Jeb setelah beberapa saat. "Aku, uh, aku harus mengurus sesuatu. Istirahatlah sejenak, dan aku akan datang menjemputmu."
Kami tidak memahami makna tersembunyi di dalam kata-katanya, hanya mendengar suaranya. Mata kami tetap terpejam. Langkah Uncle Jeb bergemerisik pelan menjauh. Kami tak tahu ke arah mana ia pergi. Lagi pula kami tak peduli.
Mereka sudah lenyap. Tak ada cara untuk mencari mereka. Tak ada harapan. Jared dan Jamie telah hilang. Mereka sangat ahli melakukan hal itu. Dan kami takkan pernah berjumpa mereka lagi.
Air dan udara malam yang lebih sejuk menyadarkan kami, dan itu sesuatu yang tidak kami inginkan. Kami berguling, kembali membenamkan wajah di pasir. Kami sangat lelah, melampaui batas kelelahan dan memasuki keadaan yang lebih serius serta menyakitkan. Kami pasti bisa tidur. Yang harus kami lakukan hanya tidak berpikir. Kami sanggup melakukannya.
Dan kami melakukannya.
Ketika kami terbangun, hari masih gelap walaupun fajar sudah mengancam di cakrawala timur. Pegunungan didereti warna merah suram. Mulut kami seperti debu, dan pertama-tama kami yakin kemunculan Uncle Jeb hanya mimpi. Tentu saja kami bermimpi.
Kepala kami lebih jernih pagi ini, dan dengan cepat kami mengamati bentuk aneh di dekat pipi kanan--sesuatu yang bukan batu atau kaktus. Kami menyentuhnya, terasa keras dan licin. Kami menyikutnya, dan muncul suara air yang bergerak-gerak di dalamnya.
Uncle Jeb benar-benar nyata, dan ia meninggalkan wadah air untuk kami.
Kami duduk hati-hati, dan terkejut ketika tubuh kami tidak patah jadi dua seperti ranting kering. Sebenarnya kami merasa lebih baik. Agaknya air itu sempat bekerja melalui beberapa bagian tubuh kami. Rasa sakitnya berkurang. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, kami kembali merasa lapar.
Jari-jari kami kaku dan kikuk ketika memutar tutup wadah air itu. Tidak begitu penuh, tapi cukup banyak air untuk mengembangkan dinding-dinding perut kami lagi. Agaknya perut kami telah menciut. Kami menghabiskan air itu, tak sudi lagi menjatah-jatah.
Kami menjatuhkan wadah air logam itu ke pasir, menciptakan suara gedebuk pelan dalam keheningan menjelang fajar. Kini kami terjaga sepenuhnya. Kami mendesah, karena lebih menyukai ketidaksadaran, lalu membenamkan kepala ke dalam tangan. Sekarang bagaimana?
"Mengapa kau memberinya air, Jeb?" desak sebuah suara marah, persis di belakang punggung kami.
Kami berputar dalam posisi berlutut. Pemandangan yang kami lihat merontokkan jantung dan memecah kesadaran kami.
Delapan manusia berdiri membentuk setengah lingkaran, mengelilingi tempatku berlutut di bawah pohon. Tak perlu dipertanyakan lagi, mereka manusia. Mereka semua. Aku belum pernah melihat wajah-wajah yang nyengir membentuk ekspresi semacam itu--belum pernah kulihat di wajah bangsaku. Bibir-bibir itu menyeringai penuh kebencian, menyingkapkan gigi yang dikertakkan seperti hewan lliar. Alis-alis itu mengerut rendah di atas mata yang terbakar kemarahan.
Enam laki-laki dan dua perempuan. Beberapa di antaranya bertubuh sangat besar, sebagian besar lebih besar dariku. Kurasakan wajahku memucat ketika menyadari mengapa tangan mereka terangkat dengan ganjil. Mereka menggenggam erat-erat sebuah benda di depan tubuh masing-masing. Mereka memegang senjata. Beberapa memegang pisau--beberapa di antaranya pisau pendek seperti yang kusimpan di dapur, beberapa lebih panjang, lalu ada pisau yang besar dan mengancam. Pisau ini tidak berguna di dapur. Melanie memasok namanya untukku: parang.
Manusia lainnya menggenggam batang panjang, sebagian logam, sebagian kayu. Pentungan.
Aku mengenali Uncle Jeb di antara mereka. Kedua tangannya memegang santai benda yang tak pernah kulihat dengan mata kepala sendiri, walaupun ada di dalam ingatan-ingatan Melanie, sama seperti pisau besar tadi. Itu senapan.
Aku melihat kengerian, tapi Melanie melihat semua ini dengan terpukau. Benaknya takjub dengan jumlah mereka. Delapan manusia yang bertahan hidup. Ia mengira Jeb sendirian atau dalam skenario terbaik, hanya ditemani dua manusia lainnya. Hati Melanie diliputi kegembiraan, melihatku betapa banyak bangsanya yang masih hidup.
Kau tolol, ujarku. Lihat mereka. Amati mereka.
Aku memaksa Melanie melihat mereka dari sudut pandangku: melihat bentuk-bentuk mengancam di balik jins kotor dan kemeja katun tipis kecokelatan yang penuh debu. Dulunya mungkin mereka manusia--dalam aarti yang ada di dalam pikiran Melanie. Tapi saat ini mereka sudah berubah. Mereka barbar, monster. Mereka mengancam kami, haus darah.
Tampak hukuman mati dalam setiap pasang mata itu.
Melanie melihat semua ini dan, walaupun bersungut-sungut, ia harus mengakui kebenaran pendapatku. Saat ini manusia-manusia tercintanya berada dalam keadaan terburuk, seperti berita-berita di koran yang kami temukan di gubuk terlantar itu. Kami sedang memandang para pembunuh.
Seharusnya kami lebih bijak; seharusnya kami mati kemarin.
Mengapa Uncle Jeb mempertahankan hidup kami untuk ini?
Aku bergidik memikirkannya. Kutelusuri sejarah-sejarah kekejaman manusia. Aku tak sanggup melihatnya. Mungkin seharusnya aku lebih berkonsentrasi. Aku tahu, ada alasan mengapa manusia membiarkan musuh mereka tetap hidup selama beberapa waktu. Mereka menginginkan beberapa hal dari benak atau tubuh musuh mereka...
Tentu saja aku langsung memikirkan satu-satunya rahasia yang mereka inginkan dariku. Rahasia yang tak akan, takkan pernah, kuceritakan kepada mereka. Tak peduli apa yang mereka lakukan padaku. Aku harus membunuh diriku sendiri lebih dulu.
Tak kubiarkan Melanie melihat rahasia yang kulindungi itu. Aku menggunakan pertahanan-pertahanan Melanie sendiri untuk melawannya, dengan membangun dinding di kepalaku. Dan aku bersembunyi di baliknya ketika memikirkan informasi itu untuk pertama kali sejak penyisipan. Belum pernah ada alasan untuk memikirkan rahasia itu sebelumnya.
Melanie, yang berada di depan dinding, bahkan nyaris tidak merasa penasaran. Ia tidak mencoba menembus dinding itu. Saat ini kekhawatirannya jauh lebih banyak, jika dibandingkan dengan kenyataan ia bukan satu-satunya yang menyimpan informasi rahasia.
Adakah artinya jika aku melindungi rahasiaku darinya? Aku tidak sekuat Melanie; aku yakin ia bisa menahan siksaan. Seberapa besar rasa sakit yang bisa kutahan, sebelum aku menyerah pada semua keinginan mereka?
Perutku bergolak. Bunuh diri adalah pilihan menjijikkan--dan lebih buruk lagi, itu juga berarti pembunuhan. Melanie akan jadi bagian dari siksaan atau kematian itu. Aku akan menunggu sampai benar-benar tak punya pilihan lain.
Tidak, mereka tak bisa melakukannya. Uncle Jeb takkan pernah membiarkan mereka melukaiku.
Uncle Jeb tidak tahu kau berada di sini, ujarku mengingatkan Melanie.
Katakan padanya!
Aku memusatkan perhatian pada wajah lelaki tua itu. Janggut putih tebalnya tidak memungkinkanku melihat bentuk mulutnya, tapi tampaknya matanya tidak membara seperti yang lain. Dari sudut mata aku bisa melihat beberapa lelaki mengalihkan pandang dariku ke Uncle Jeb. Mereka menunggu jawaban atas pertanyaan yang menyadarkanku akan kehadiran mereka. Uncle jeb menatapku, mengabaikan mereka.
Tak bisa kukatakan kepadanya, Melanie. Ia takkan percaya. Dan jika mereka menganggapku berbohong, mereka akan mengira aku adalah Pencari. Mereka pasti cukup berpengalaman, sehingga hanya tahu Pencari-lah yang akan datang ke sini berbekal kebohongan, berbekal cerita yang dirancang untuk memungkinkan penyusupan.
Melanie langsung memahami kebenaran pikiranku. Bahkan kata Pencari saja membuatnya mengerut ketakutan. Dan ia tahu orang-orang asing ini akan menunjukkan reaksi yang sama.
Lagi pula tak ada gunanya. Aku adalah jiwa--itu cukup bagi mereka.
Satu-satunya manusia yang memegang parang--lelaki terbesar di sana, dengan rambut hitam, kulit putih ganjil, dan mata biru cerah--mengeluarkan suara yang menunjukkan rasa jijik dan meludah ke tanah. Ia melangkah maju, lalu perlahan-lahan mengangkat pisau panjang itu.
Lebih baik cepat daripada pelan-pelan. Lebih baik tangan brutal itu, dan bukan tanganku yang membunuh kami. Lebih baik aku tidak mati sebagai mahluk kejam yang bertanggung jawab atas darah Melanie sekaligus darahku sendiri.
"Tunggu, Kyle." Kata-kata Jeb tidak terburu-buru, nyaris santai, tapi lelaki bertubuh besar itu berhenti. Ia nyengir, lalu berbalik menghadap paman Melanie.
"Kenapa? Katamu kau sudah memastikan. Dia salah satu dari mereka."
Aku mengenali suara itu. Itu orang yang sama yang bertanya kepada Jeb mengapa ia memberiku air.
"Well, ya, itu pasti. Tapi ini agak rumit."
"Bagaimana bisa?" Lelaki lain yang mengucapkkan pertanyaan itu. Ia berdiri di samping Kyle yang bertubuh besar dan berambut gelap. Mereka sangat mirip, sehingga pasti kakak-beradik.
"Dia juga keponakanku."
"Tidak lagi. Bukan lagi," ujar Kyle datar. Ia kembali meludah, dan sengaja maju selangkah ke arahku dengan pisau teracung. Dari bahunya yang condong ke depan bisa kulihat kata-kata takkan bisa lagi menghentikannya. Kupejamkan mata.
Terdengar dua klik logam tajam, dan seseorang terkesiap. Mataku kembali terbuka.
"Kubilang tunggu, Kyle." Suara Uncle Jeb masih santai, tapi kini senapan panjang tergenggam erat di tangannya, moncongnya terarah ke punggung Kyle. Kyle terpaku hanya beberapa langkah dariku, parangnya teracung tak bergerak di udara, di atas bahunya.
"Jeb," ujar saudara laki-laki Kyle ketakutan, "apa maumu?"
"Menjauhlah dari gadis itu, Kyle."
Kyle berbalik memunggungi kami, berputar marah menghadap Jeb. "Itu bukan gadis, Jeb!"
Jeb mengangkat bahu; posisi senapannya masih tak berubah di kedua tangannya, masih mengarah kepada Kyle.
"Ada beberapa hal yang harus dibahas."
"Mungkin si dokter bisa mempelajari sesuatu darinya," ujar suara parau perempuan.
Aku ciut mendengar kata-katanya, mendengar ketakutan terburukku di dalamnya. Ketika Jeb tadi menyebutku keponakannya dengan tolol aku membiarkan sepercik harapan menyala--mungkin akan muncul rasa iba. Aku tolol jika mengira seperti itu, bahkan untuk sedetik saja. Kematian adalah satu-satunya rasa iba yang bisa kuharapkan dari mahluk-mahluk ini.
Kutatap perempuan yang baru saja bicara itu, dan aku terkejut melihat ia sama tuanya dengan Jeb, bahkan mungkin lebih tua. Rambutnya tidak berwarna putih, melainkan abu-abu gelap. Karena itulah aku tidak memperhatikan usianya. Wajahnya penuh keriput, dan semua terlipat membentuk garis-garis kemarahan. Tapi ada sesuatu yang kukenal dari ekspresi wajah itu, di balik garis-garis amarahnya.
Melanie menghubungkan wajah tua ini dengan wajah lain yang lebih halus di dalam ingatannya.
"Aunt Maggie? Kau di sini? Bagaimana bisa? Apakah Sharon--"
Itu semua kata-kata Melanie, tapi mengalir keluar dari mulutku, dan aku tak sanggup menghentikannya. Setelah begitu lama bersama-sama di padang gurun, ia jadi semakin kuat atau aku semakin lemah. Atau mungkin karena aku sedang berkonsentrasi untuk mengetahui dari mana pukulan kematian itu bakal datang. Aku sedang bersiap-siap menghadapi pembunuh kami, tapi Melanie menghadapi reuni keluarga.
Melanie hanya sempat mengucapkan setengah teriakan terkejutnya. Perempuan yang jauh lebih tua bernama Maggie menerjang dengan kecepatan yang mengingkari tubuh rapuhnya. Ia tidak mengangkat tangannya yang memegang linggis hitam. Itu tangan yang sedang kuawasi, jadi aku tidak melihat tangan satunya terayun untuk menampar wajahku keras-keras.
Kepalaku tersentak ke belakang, lalu ke depan. Ia menamparku lagi.
"Kau tidak bisa menipu kami, parasit. Kami tahu cara kerjamu. Kami tahu betapa baik kau bisa menirukan kami."
Kurasakan darah keluar di pipi bagian dalam.
Jangan berbuat seperti itu lagi, ujarku memarahi Melanie. Sudah kubilang apa yang akan mereka pikirkan.
Melanie kelewat terkejut untuk menjawab.
"Wah, Maggie," Jeb memulai, nada suaranya menenangkan.
"Jangan bilang 'Wah, Maggie' kepadaku. Dasar lelaki tua tolol! Parasit itu mungkin memimpin satu legiun bangsanya menuju kemari." Aunt Maggie menjauh dariku, matanya menilai sikap diamku seakan-akan aku ular yang bergelung. Ia berhenti di samping saudara laki-lakinya.
"Aku tidak melihat yang lain," tukas Jeb. "Hei" serunya, dan aku terenyak. Aku bukan satu-satunya. Jeb melambaikan tangan kirinya di atas kepala, senapan masih tergenggam di tangan kanan. "Di sini!"
"Diam," gerutu Maggie. Didorongnya dada Jeb. Walaupun aku sangat yakin dengan kekuatan perempuan tua itu, Jeb tidak goyah.
"Dia sendirian, Mag. Dia bisa dibilang sudah mati ketika aku menemukannya. Sekarang keadaannya juga tidak begitu baik. Kaki seribu tidak akan mengorbankan bangsanya dengan cara seperti ini. Mereka pasti akan datang menolong, jauh lebih cepat daripadaku. Apa pun dia, dia sendirian."
Aku melihat gambaran serangga panjang berkaki banyak di dalam kepalaku, tapi tak bisa melihat hubungannya dengan perkataan Uncle Jeb.
Dia sedang membicarakanmu, Melanie menerjemahkan. Diletakkannya gambaran serangga jelek itu di samping ingatanku mengenai sesosok jiwa berwarna perak cemerlang. Aku tidak melihat adanya kesamaan.
Aku heran dari mana Uncle Jeb tahu seperti apa bentukmu, renung Melanie. Pada awalnya ingatanku mengenai bentuk asli jiwa merupakan pengetahuan baru bagi Melanie.
Aku tak punya waktu untuk merenung bersama Melanie. Jeb menghampiriku, dan yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Tangan Kyle terangkat di dekat bahu Jeb, siap menahan atau menyingkirkannya. Aku tak yakin.
Jeb memindahkan senapan ke tangan kiri, lalu mengulurkan tangan kanannya kepadaku. Aku mengawasinya dengan cemas, menunggu tangan itu memukulku.
"Ayo," desaknya lembut. "Seandainya bisa membawamu sejauh itu, aku akan membawamu pulang semalam. Kau harus berjalan kaki agak jauh."
"Tidak!" gerutu Kyle.
"Aku akan membawanya pulang," kata Jeb, untuk pertama kali aku mendengar nada yang agak keras di dalam suaranya. Di balik janggut itu rahangnya membentuk garis tegas.
"Jeb!" protes Maggie.
"Itu rumahku, Mag. Akan kulakukan apa yang kuinginkan."
"Si tua tolol!" bentak Maggie lagi.
Jeb mengulurkan tangan, meraih tanganku yang terkepal di paha. Ia menarikku berdiri. Bukan dengan kasar, tapi seakan terburu-buru. Tapi bukankah memperpanjang hidupku untuk alasan-alasan yang ia miliki merupakan bentuk kekejaman terparah?
Aku bergoyang-goyang tidak stabil. Kakiku tidak terlalu bisa kurasakan. Yang ada hanya perasaan seperti ditusuk-tusuk jarum keitka darah mengalir turun.
Terdengar desis tidak setuju dari belakang Jeb. Dikeluarkan lebih dari satu mulut.
"Oke, siapapun kau," kata Jeb kepadaku, suaranya tetap ramah. "Ayo, pergi dari sini sebelum udara memanas."
Lelaki yang agaknya saudara laki-laki Kyle itu menyentuh lengan jeb.
"Kau tidak boleh menunjukkan tempat tinggal kita, Jeb."
"Kurasa itu tak masalah," ujar Maggie kasar. "Dia tidak akan punya peluang untuk bercerita."
Jeb mendesah. Dari leher ia menarik bandana yang tersembunyi di balik janggut.
"Ini konyol," gumamnya. Tapi ia menggulung kain kotor yang kaku oleh keringat kering itu menjadi penutup mata.
Aku tetap diam ketika Jeb mengikatkan kain itu menutupi mataku. Kuperangi rasa panik yang semakin meningkat karena aku tak bisa melihat musuh-musuhku.
Aku tak bisa melihat, tapi tahu Jeb meletakkan sebelah tangannya di punggungku dan menuntunku; tak satu un dari mereka bisa bersikap begitu lembut.
Kami mulai berjalan, kurasa menuju utara. Mula-mula tak seorang pun bicara--yang terdengar hanya suara pasir tergilas di bawah banyak kaki. Tanahnya rata, tapi aku terus-menerus tersandung kakiku sendiri yang mati rasa. Jeb bersikap sabar; tangannya menuntunku nyaris bisa dikatakan sangat kesatria.
Kurasakan terbitnya matahari ketika kami berjalan. Beberapa langkah kaki terdengar lebih cepat daripada lainnya. Mereka bergerak di depan kami, sehingga sulit didengar. Tampaknya seolah-olah hanya sebagian kecil yang tetap tinggal bersamaku dan Jeb. Agaknya aku tidak kelihatan memerlukan banyak pengawal--tubuhku lemah akibat kelaparan, dan aku terhuyung-huyung di setiap langkah; kepalaku pening dan kosong.
"Kau tidak berencana untuk bercerita kepadanya, bukan?"
Itu suara Maggie; beberapa puluh sentimeter di belakangku, dan kedengarannya seperti menuduh.
"Dia berhak tahu," jawab Jeb. Nada keras kepala itu kembali terdengar di dalam suaranya.
"Perbuatanmu kejam, Jebediah."
"Hidup memang kejam, Maggie."
Sulit untuk memutuskan siapa yang lebih menakutkan di antara keduanya. Apakah Jeb, yang tampak begitu ngotot ingin mempertahankan hidupku? Atau Maggie, yang pertama kali menyarankan dokter, sebutan yang memenuhiku dengan ketakutan yang bersifat naluriah dan memualkan? Tapi perempuan tua itu tampaknya lebih mengkhawatirkan soal kekejaman daripada saudara laki-lakinya.
Selama beberapa jam kami kembali berjalan dalam keheningan. Ketika kakiku roboh, Jeb mendudukkanku di tanah dan mendekatkan tempat air ke bibirku, seperti yang dilakukannya malam itu.
"Beritahu jika kau sudah siap," ujar Jeb. Suaranya ramah, walaupun aku tahu itu interpretasi keliru.
"Kenapa kau berbuat seperti ini, Jeb?" tanya seorang lelaki. Aku pernah mendengar suara itu sebelumnya; salah satu kakak-beradik itu. "Demi Doc? Seharusnya kau bisa bilang begitu kepada Kyle. Tak perlu menodong dengan senapan."
"Kyle perlu lebih sering ditodong senapan," gumam Jeb.
"Katakan kalau ini bukan masalah simpati," lanjut lelaki itu,
"Setelah semua yang kausaksikan..."
"Setelah semua yang kausaksikan, jika aku belum belajar soal belas kasih, diriku takkan banyak berarti. Tapi tidak, ini bukan masalah simpati. Seandainya aku punya cukup banyak simpati untuk mahluk malang ini, aku pasti sudah membiarkannya mati."
Aku menggigil dalam udara sepanas oven.
"Lalu apa?" desak saudara laki-laki Kyle.
Hening panjang, lalu Jeb menyentuh tanganku. Aku meraihnya. Aku perlu pertolongan untuk kembali berdiri. Tangan Jeb yang satu menekan punggungku, dan aku mulai berjalan lagi.
"Rasa penasaran," ujar Jeb pelan.
Tak seorang pun menjawab.
Ketika kami berjalan, aku merenungkan beberapa fakta yang sudah pasti. Satu, aku bukan jiwa pertama yang mereka tangkap. Sudah ada serangkaian rutinitas di sini. "Doc" pernah mencoba memperoleh jawaban dari jiwa-jiwa lain sebelum aku.
Dua, Doc belum berhasil. Seandainya ada jiwa yang batal bunuh diri dan menyerah di bawah siksaan manusia, mereka takkan memerlukanku sekarang. Kematianku bakal cepat dan menyenangkan.
Tapi anehnya aku tak bisa memaksa diri untuk mengharapkan kematian cepat, atau mencoba mewujudkannya. Mudah untuk bunuh diri, bahkan tanpa harus melakukannya sendiri. Yang harus kulakukan hanya menceritakan kebohongan--berpura-pura aku Pencari, mengatakan saat ini rekan-rekanku sedang mencariku, serta membuat da mengancam. Atau mengatakan yang sebenarnya--bahwa Melanie tetap hidup di dalam diriku, dan dialah yang membawaku kemari.
Lalu mereka akan melihat kebohongan lain, kebohongan yang sangat tidak tertanggungkan--gagasan bahwa manusia bisa tetap hidup setelah penyisipan. Gagasan ini begitu menggoda untuk dipercaya dari sudut pandang mereka, begitu licik, sehingga mereka akan semakin yakin aku Pencari, melebihi perkataanku sendiri. Mereka akan menganggap gagasan itu jebakan, menyingkirkanku dengan cepat, lalu mencari tempat lain untuk bersembunyi, jauh dari sini.
Mungkin kau benar, Melanie mengiyakan. Itulah yang akan kulakukan.
Tapi aku belum merasa kesakitan, sehingga sulit bagiku untuk memilih bentuk bunuh diri mana pun; naluriku untuk bertahan hidup membungkam mulutku. Ingatan mengenai pertemuan terakhir dengan Penghibur-ku--saat yang begitu beradab, sehingga tampaknya terjadi di planet lain--berkelebat di kepalaku. Saat itu Melanie menantangku untuk menyingkirkan dirinya. Itu dorongan yang tampaknya bersifat bunuh diri. Tapi ia hanya menggertak. Aku ingat diriku berpikir betapa sulit merenungkan kematian dari kursi yang nyaman.
Semalam aku dan Melanie menginginkan kematian, tapi saat itu kematian hanya beberapa senti jauhnya. Kini setelah aku kembali berdiri di atas kakiku sendiri, rasanya berbeda.
Aku juga tidak ingin mati, bisik Melanie. Tapi mungkin kau keliru, mungkin bukan itu alasan mereka mempertahankan hidup kita. Aku tidak mengerti mengapa mereka... Ia tidak ingin membayangkan hal-hal yang mungkin akan mereka lakukan kepada kami, dan aku yakin bayangan Melanie jauh lebih buruk daripada bayanganku sendiri. Jawaban apa yang teramat sangat mereka inginkan darimu?
Pertanyaan yang berani. Tapi aku memang belum merasa kesakitan...
Satu jam lagi berlalu--matahari tepat di atas kepala, panasnya bagai mahkota api di rambutku--ketika suara yang kudengar berubah. Langkah kaki menggerus pasir nyaris tak bisa lagi kudengar, berubah menjadi gema-gema di depanku. Kaki Jeb masih menggerus pasir seperti kakiku, tapi seseorang di depan kami telah mencapai tempat lain.
"Sekarang hati-hati," Jeb mengingatkan. "Awas, kepalamu."
Aku bimbang, tak yakin apa yang harus kuawasi, atau bagaimana cara mengawasinya dengan mata terpejam. Tangan Jeb meningggalkan punggungku dan menekan kepalaku, menyuruhku menunduk. Aku membungkuk. Leherku kaku.
Jeb menuntunku maju lagi, dan aku mendengar langkah-langkah kami menciptakan bunyi menggema yang sama. Tanahnya tidak terkuak seperti pasir, tidak goyah seperti batu. Melainkan padat dan datar di bawah kakiku.
Matahari lenyap--aku tak bisa lagi merasakan cahayanya membakar kulit atau menghanguskan rambutku.
Aku maju selangkah lagi, dan udara baru menyentuh wajahku. Bukan angin sepoi-sepoi. Ini udara diam-dan aku bergerak memasukinya. Angin padang gurun kering itu lenyap. Udara tak bergerak dan lebih sejuk. Terasa sedikit kelembaban di dalamnya, bau apak yang bisa kucium dan kurasakan.
Muncul begitu banyak pertanyaan di benakku, juga di benak Melanie. ia ingin menyuarakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi aku diam saja. Kini tak satu pun perkataannya ataupun perkataanku bisa membantu kami.
"Oke, kau bisa menegakkan tubuh," ujar Jeb.
Aku mengangkat kepala perlahan-lahan.
Bahkan dengan penutup mata, bisa kukatakan tak ada cahaya. Benar-benar gelap di sekeliling tepi bandana. Aku bisa mendengar yang lain di belakangku menyeret kaki tidak sabar, menungguku bergerak maju.
"Lewat sini," kata Jeb kembali menuntunku. Langkah kami menggema di dekat kami--agaknya ruangan tempat kami berada cukup kecil. Aku mendapati diriku otomatis menunduk.
Kami maju beberapa langkah, lalu mengitari lengkungan tajam yang sepertinya mengembalikan kami ke tempat kedatangan kami. Tanahnya mulai miring ke bawah. Sudutnya semakin curam bersama setiap langkah, dan Jeb mengulurkan tangan kasarnya agar aku tidak jatuh. Aku tak tahu berapa lama aku terselip dan tergelincir melewati kegelapan. Perjalanan itu mungkin terasa lebih panjang daripada sesungguhnya, karena setiap menit diperlambat oleh kengerianku.
Kami kembali berbelok, lalu lantai mulai menanjak. Kakiku begitu mati rasa dan kaku sehingga ketika jalurnya semakin curam, Jeb harus setengah menyeretku ke atas. Semakin jauh kami berjalan, udara semakin apak dan lembap, tapi kegelapan tidak berubah. Yang terdengar hanya langkah kami dan gema-gemanya yang dekat.
Jalur itu berubah mendatar dan mulai berliku-liku seperti ular. Akhirnya. Akhirnya cahaya muncul di sekeliling bagian atas dan bawah penutup mataku. Aku berharap penutup itu bergeser, karena aku terlalu takut untuk membukanya sendiri. Tampaknya takkan begitu menakutkan jika aku bisa melihat di mana aku berada dan siapa yang bersamaku.
Bersamaan dengan cahaya, terdengar suara. Suara itu aneh, gumaman percakapan pelan. Kedengarannya nyaris seperti suara air terjun.
Gumam percakapan itu terdengar semakin keras ketika kami bergerak maju. Dan ketika kami semakin dekat, semakin tak terdengar seperti air. Terlalu bervariasi, nada-nada tinggi-rendah bercampur dan bergema. Seandainya tidak begitu sumbang pasti kedengarannya seperti versi buruk musik konstan yang kudengar dan kunyanyikan di Singing World. Kegelapan penutup matanya cocok dengan ingatan itu; ingatan mengenai kebutaan.
Melanie memahami keriuhan itu lebih dulu. Aku tak pernah mendengar suara semacam itu, karena tak pernah bersama-sama manusia sebelumnya.
Itu perselisihan, Melanie tersadar. Kedengarannya begitu banyak orang sedang berselisih.
Ia tertarik dengan suara itu. Kalau begitu, apakah ada lebih banyak manusia lagi di sini? Bahkan jumlah delapan orang pun telah mengejutkan kami. Tempat apakah ini?
Tangan-tangan menyentuh tengkukku, dan aku menjauhi mereka.
"Tenang," kata Jeb. Ditariknya penutup mata dari mataku.
Aku mengerjap perlahan-lahan, dan bayang-bayang di sekelilingku berubah jadi bentuk-bentuk yang bisa kupahami: dinding-dinding kasar dan tidak rata; langit-langit penuh lubang; lantai usang berdebu. Kami di bawah tanah, di suatu tempat, di dalam gua yang terbentuk alami. Tak mungkin kami berada sedalam itu. Kurasa perjalanan kami ke atas lebih panjang daripada perjalanan kami ke bawah.
Dinding dan langit-langit batu itu berwarna cokelat keunguan gelap dan dipenuhi lubang dangkal seperti keju Swiss. Pinggiran lubang - lubang yang letaknya di sebelah bawah lebih tumpul, tapi lingkaran-lingkaran di atas kepalaku lebih tegas dan pinggirannya tampak tajam.
Cahaya datang dari lubang bulat di depan kami. Bentuk lubang itu tidak seperti lubang - lubang yang memenuhi gua, tapi lebih besar. Ini pintu masuk, ambang pintu ke tempat yang lebih terang. Melanie bersemangat, terpukau oleh konsep ada lebih banyak manusia. Aku menahan diri, mendadak khawatir kebutaan mungkin lebih baik daripada penglihatan.
Jeb mendesah. "Maaf," gumamnya, sangat pelan sehingga aku yakin hanya diriku yang mendengarnya.
Aku mencoba menelan ludah, tapi tak bisa. Kepalaku mulai berputar, tapi itu mungkin karena lapar. Ketika Jeb mendorongku melewati lubang besar itu, kedua tanganku gemetar seperti dedaunan tertiup angin kencang.
Terowongan itu berakhir di bilik yang sangat luas, sehingga pertama-tama aku tak bisa memahami apa yang disaksikan mataku. Langit-langitnya terlalu terang dan terlalu tinggi--seperti langit buatan. Kucoba melihat apa yang meneranginya, tapi langit-langit itu mengirimkan tembok-tembok cahaya tajam yang menyakiti mata.
Aku berharap percakapan itu terdengar semakin keras, tapi mendadak sangat hening di dalam ruang gua yang besar.
Lantainya suram dibandingkan langit-langit cemerlang yang tinggi di atas sana. Perlu sejenak bagi mataku untuk memahami semua bentuk itu.
Kerumunan. Tak ada kata lain untuk itu. Kerumunan manusia yang berdiam diri tak bergerak, semua menatapku garang, penuh kebencian, sama seperti yang kulihat fajar tadi.
Melanie kelewat terpukau untuk melakukan sesuatu, kecuali menghitung. 10, 15, 20... 25, 26, 27...
Aku tak peduli ada berapa banyak manusia. Aku berusaha mengatakan kepada Melanie betapa tak berartinya hal itu. Tak perlu dua puluh orang untuk membunuhku. Untuk membunuh kami. Aku mencoba membuat Melanie melihat betapa membahayakan posisi kami, tapi saat itu ia tak bisa kuperingatkan lagi. ia terhanyut dalam dunia manusia, yang tak pernah ia impikan keberadaannya di sini.
Seorang lelaki maju dari kerumunan, dan pertama-tama mataku tertuju pada kedua tangannya, mencari senjata. Kedua tangannya terkepal tapi tak ada benda-benda mengancam lainnya. Mataku, yang sedang menyesuaikan diri dengan cahaya menyilaukan itu melihat warna kulit lelaki itu yang terbakar matahari, lalu mengenalinya.
Tercekik harapan mendadak yang membuatku pening, aku mengangkat mata memandang wajahnya.
---

















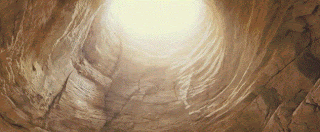












0 comments:
Post a Comment