Mengaku
Bayangan itu besar dan aneh bentuknya, menjulang di atas tubuhku, sangat berat, dan berayun mendekati wajahku.
Kurasa aku hendak berteriak, tapi teriakanku terperangkap di dalam tenggorokan, dan yang keluar hanya decit pelan.
"Sst, ini aku," bisik Jamie. Sesuatu yang besar dan bulat berguling dari bahunya dan berdebum pelan ke lantai. Ketika benda itu lenyap, aku bisa melihat bayangan kecil Jamie yang sebenarnya, dilatari cahaya bulan.
Sejenak aku tersengal, tanganku mencengkeram leher.
"Maaf," bisik Jamie. Ia duduk di tepi kasur. "Kurasa perbuatanku sangat tolol. Aku berusaha untuk tidak membangunkan Doc. Aku bahkan tidak berpikir, betapa aku akan membuatmu ketakutan. Kau baik-baik saja?" Ia menepuk-nepuk pergelangan kakiku-bagian tubuhku yang terdekat dengannya.
"Tentu," ujarku, masih tersengal.
"Maaf," gumamnya lagi.
"Apa yang kaulakukan di sini, Jamie? Bukankah kau seharusnya tidur?"
"Itulah sebabnya aku di sini. Uncle Jeb mendengkur keras sekali, sehingga kau mungkin takkan percaya. Aku tidak tahan lagi."
Jawaban Jamie tak masuk akal. "Bukankah kau biasa tidur bersama Jeb?"
Jamie menguap, lalu membungkuk untuk membuka pengikat kasur gulung besar yang tadi dijatuhkannya ke lantai. "Tidak, aku biasanya tidur bersama Jared. Ia tidak mendengkur. Tapi kau sudah tahu itu."
Memang.
"Lalu mengapa kau tidak tidur di kamar Jared? Kau takut tidur sendirian?" Aku takkan menyalahkannya untuk itu. Tampaknya di sini selalu menakutkan.
"Takut?" Jamie menggerutu, tersinggung. "Tidak. Ini kamar Jared. Dan kamarku."
"Apa?" aku terkesiap. "Jeb menempatkanku di kamar Jared?"
Aku tidak percaya ini. Jared akan membunuhku. Tidak, ia akan membunuh Jeb lebih dulu, lalu membunuhku.
"Ini kamarku juga. Dan kubilang pada Jeb, kau bisa memakainya."
"Jared akan marah besar," bisikku.
"Aku bisa melakukan apa pun yang kuinginkan dengan kamarku," bantah Jamie, tapi ia lalu menggigit bibir. "Kita tidak akan memberitahunya. Jared tak perlu tahu."
Aku mengangguk. "Ide bagus."
"Kau tidak keberatan aku tidur di sini, kan? Uncle Jeb benar-benar berisik."
"Tidak. Aku tidak keberatan. Tapi, Jamie, kurasa kau tidak boleh melakukannya."
Jamie memberengut, mencoba tampak tegar, bukannya terluka.
"Kenapa tidak?"
"Karena tidak aman. Terkadang orang datang mencariku di malam hari."
Matanya membelalak. "Benarkah?"
"Jared selalu memegang senapan--sehingga mereka pergi."
"Siapa?"
"Aku tak tahu--kadang-kadang Kyle. Tapi pasti masih ada orang-orang lain yang berada di sini."
Jamie mengangguk. "Lebih banyak lagi alasan mengapa aku harus tetap di sini. Doc mungkn perlu bantuan."
"Jamie--"
"Aku bukan anak-anak, Wanda. Aku bisa menjaga diriku sendiri."
Membantah jelas hanya akan membuat Jamie semakin keras kepala. "Setidaknya, pakailah tempat tidurnya," ujarku menyerah.
"Aku akan tidur di lantai. Ini kamarmu."
"Itu keliru. Kau tamu."
Aku mendengus pelan. "Ha. Tidak, tempat tidurnya untukmu."
"Tak mungkin." Jamie berbaring di kasur gulung, lalu melipat kedua lengannya rapat-rapat di dada.
Sekali lagi aku melihat membantah adalah pendekatan yang keliru untuk Jamie. Well, yang ini bisa langsung kuperbaiki setelah ia tidur. Jamie tidur sangat nyenyak, sampai nyaris bisa disebut koma. Melanie duku bisa menggendongnya ke mana pun setelah ia tertidur.
"Kau bisa memakai bantalku," kata Jamie kepadaku, seraya menepuk-nepuk bantal di sebelah tempatnya berbaring. "Kau tak perlu meringkuk di ujung sana."
Aku mendesah, tapi merangkak ke bagian atas tempat tidur.
"Nah, begitu," ujarnya setuju. "Sekarang, bisakah kau melemparkan bantal Jared kepadaku?"
Aku bimbang, hendak meraih bantal di bawah kepalaku. Jamie melompat bangun, membungkuk ke arahku, lalu meraih bantal yang lain. Aku kembali mendesah.
Sejenak kami berbaring dalam keheningan, mendengarkan siulan rendah napas Doc.
"Dengkuran Doc menyenangkan, bukan?" bisik Jamie.
"Tidak membuatmu terjaga," jawabku mengiyakan.
"Kau lelah?"
"Ya."
"Oh."
Aku menunggu Jamie mengatakan sesuatu lagi, tapi ia diam saja.
"Ada sesuatu yang kauinginkan?" tanyaku.
Jamie tidak langsung menjawab, tapi bisa kurasakan pergulatannya, jadi aku menunggu.
"Kalau aku menanyakan sesuatu, maukah kau mengatakan yang sebenarnya?"
Giliranku bimbang. "Aku tidak mengetahui semua hal," elakku.
"Yang ini kau pasti tahu. Ketika kami sedang berjalan... aku dan Jeb... dia menceritakan beberapa hal. Hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Tapi aku tak tahu apakah dia benar."
Mendadak melanie sangat hadir di dalam kepalaku.
Bisikan Jamie sulit didengar, lebih pelan daripada napasku. "Menurut Uncle Jeb, Melanie mungkin masih hidup. Maksudku, dia berada di dalam sana bersamamu."
Jamie-ku. Melanie mendesah.
Aku tak menjawab keduanya.
"Aku tak tahu apakah itu bisa terjadi. Apakah itu terjadi?" Suara Jamie pecah, dan aku bisa mendengar ia memerangi air mata. Ia bukan anak cengeng, dan aku kembali sangat sedih untuknya, dua kali dalam satu hari. Perasaan nyeri menembus dadaku.
"Benarkah, Wanda?"
Katakan kepadanya. Kumohon, katakan aku mencintainya.
"Kenapa kau tidak mau menjawabku?" Kini jamie benar-benar menangis, tapi ia mencoba meredam suaranya.
Aku merangkak turun dari tempat tidur, lalu menjejalkan diri ke celah keras di antara tempat tidur dan kasur gulung, mengulurkan tangan ke dada Jamie yang bergetar. Kusurukkan kepalaku ke rambutnya, dan kurasakan air matanya, hangat di leherku.
"Apakah Melanie masih hidup, Wanda? Kumohon?"
Mungkin Jamie hanyalah alat. Lelaki tua itu bisa saja mengutus Jamie khusus untuk ini; Jeb cukup pintar untuk melihat betapa mudah Jamie mematahkan pertahananku. Mungkin Jeb mencari penegasan atas teorinya, dan ia tak segan-segan menggunakan anak ini untuk mendapatkannya. Apa yang akan ia perbuat, ketika meyakini kebenaran berbahaya itu? Bagaimana ia akan menggunakan informasi itu? Kurasa ia tidak bermaksud jahat, tapi bisakah aku memercayai penilaianku sendiri? Manusia adalah mahluk penipu, pengkhianat. Aku tak bisa mengantisipasi niat mereka yang lebih kelam, karena hal-hal semacam itu tak terpikirkan oleh spesiesku.
Tubuh Jamie berguncang-guncang di sampingku.
Ia menderita, teriak Melanie. Sia-sia Melanie melawan kendaliku.
Tapi aku tak bisa menyalahkan Melanie, seandainya ini ternyata merupakan kesalahan besar. Aku tahu siapa yang kini sedang bicara.
"Melanie berjanji akan kembali, bukan?" gumamku. "Akankah dia mengingkari janjinya kepadamu?"
Jamie melingkarkan kedua tangannya di pinggangku dan menggayutiku untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit ia berbisik, "Aku sayang padamu, Mel."
"Dia sayang padamu juga. Dia sangat senang kau ada di sini dan aman."
Jamie diam cukup lama sehingga air mata di kulitku mengering, meninggalkan debu asin halus.
"Apakah semua orang seperti itu?" bisik Jamie, lama setelah aku mengira ia telah terlelap. "Apakah semua orang tetap tinggal di dalam sana?"
"Tidak," ujarku sedih. "Tidak. Melanie istimewa."
"Dia kuat dan berani."
"Sangat."
"Apakah menurutmu..." Jamie berhenti untuk menghela napas. "Apakah menurutmu Dad mungkin masih berada di sana juga?"
Aku menelan ludah, mencoba mendorong gumpalan itu lebih jauh ke dalam tenggorokan. Sia-sia. "Tidak, Jamie. Tidak, kurasa tidak. Tidak seperti Melanie."
"Kenapa?"
"Karena ayahmu membawa para Pencari untuk menangkapmu. Well, jiwa di dalamnya yang melakukan itu. Ayahmu takkan membiarkan itu terjadi, kalau saja dia masih di sana. Melanie tak pernah membiarkanku melihat di mana kabin itu berada. Dan untuk waktu yang lama sekali, dia bahkan tidak membiarkanku tahu kau ada. Dia tidak membawaku kemari, sampai merasa yakin aku takkan melukaimu."
Terlalu banyak informasi. Selesai bicara, baru kusadari Doc tak lagi mendengkur. Aku tidak bisa mendengar suara napasnya. Tolol. Diam-diam kumaki diriku sendiri.
"Wow," ujar Jamie.
Aku berbisik di telinganya, begitu dekat sehingga tak mungkin Doc bisa menguping. "Ya, Melanie sangat kuat."
Jamie berusaha keras mendengarku. Ia cemberut, lalu melirik lubang menuju lorong gelap. Ia menyadari hal yang sama, karena ia mengarahkan wajah ke telingaku dan kembali berbisik, lebih pelan daripada sebelumnya. "Mengapa kau bersedia melakukannya? Tidak melukai kami? Bukankah itu yang kauinginkan?"
"Tidak. Aku tidak ingin melukaimu."
"Mengapa?"
"Aku dan kakakmu telah... menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Dia membagimu untuk kami berdua. Dan... aku mulai... sayang padamu juga."
"Dan Jared juga?"
Sejenak aku menggertakkan gigi, merasa kesal karena dengan mudah Jamie bisa menghubungkan kedua hal itu. "Tentu saja aku juga tak menginginkan apa pun melukai Jared."
"Jared membencimu," ujar Jamie. Jelas ia sedih melihat kenyataan itu.
"Ya. Semua orang membenciku." Aku mendesah. "Aku tak bisa menyalahkan mereka."
"Jeb tidak membencimu. Aku juga."
"Kau mungkin akan membenciku, setelah lebih banyak merenungkannya."
"Tapi kau bahkan tidak berada di sini ketika mereka mengambil alih. Kau tidak memilih ayahku atau ibuku atau Melanie. Saat itu kau berada di luar angkasa, bukan?"
"Ya, tapi aku adalah aku, Jamie. Aku melakukan apa yang dilakukan jiwa. Aku punya banyak inang sebelum Melanie, dan tak ada yang menghentikanku untuk... merampas kehidupan. Berulang kali. Begitulah cara hidupku."
"Apakah Melanie membencimu?"
Sejenak aku berpikir. "Dia tidak terlalu membenciku seperti dulu."
Tidak. Aku sama sekali tidak membencimu. Tidak lagi.
"Katanya dia sama sekali tak membenciku," gumamku, nyaris tak terdengar.
"Bagaimana... bagaimana kabarnya?
"Dia senang berada di sini. Dia begitu bahagia berjumpa denganmu. Dia bahkan tak peduli apakah mereka hendak membunuh kami."
Jamie mengejang di bawah lenganku. "Mereka tidak bisa membunuhmu! Tidak bisa, jika Mel masih hidup!"
Kau membuatnya sedih, keluh Melanie. Kau tidak perlu berkata begitu.
Tidak bakal mudah baginya, kalau ia tidak siap.
"Mereka takkan percaya itu, Jamie," bisikku. "Mereka akan mengira aku berbohong untuk menipumu. Kalau kau menceritakan hal ini, mereka hanya akan semakin bernafsu membunuhku. Hanya Pencari yang berbohong."
Kata itu membuat Jamie bergidik.
"Tapi kau tidak bohong. Aku tahu itu," ujar Jamie setelah beberapa saat.
Aku mengangkat bahu.
"Aku takkan membiarkan mereka membunuh Mel."
Suara Jamie, walaupun sepelan napas, terdengar garang penuh tekad. Aku terpaku, membayangkan dirinya semakin terlibat dengan situasi ini, semakin terlibat denganku. Kubayangkan orang-orang barbar yang tinggal bersamanya. Apakah usia muda akan melindungi Jamie dari mereka, seandainya ia mencoba melindungiku? Aku ragu. Pikiranku campur aduk, mencari cara untuk mencegah Jamie tanpa memicu kekeraskepalaannya.
Jamie bicara sebelum aku bisa mengatakan sesuatu; mendadak ia berubah tenang, seolah jawabannya sudah jelas di depannya. "Jared akan memikirkan sesuatu. Dia selalu begitu."
"Jared juga tidak bakal percaya. Dia akan menjadi yang paling marah di antara mereka semua."
"Bahkan seandainya tidak percaya, dia akan melindungi Mel, sekadar berjaga-jaga."
"Akan kita lihat nanti," gumamku. Nanti akan kucari kata-kata yang sempurna--bantahan yang tidak akan terdengar seperti bantahan.
Jamie diam, berpikir. Akhirnya napasnya melambat dan mulutnya terbuka. Aku menunggu sampai yakin ia sudah tidur nyenyak, lalu aku menghampirinya, dan dengan sangat hati-hati memindahkannya dari lantai ke tempat tidur. Ia lebih berat daripada dulu, tapi aku berhasil. Ia tidak terbangun.
Kuletakkan bantal Jared di tempatnya, lalu kurebahkan tubuhku ke atas kasur gulung.
Well, pikirku. Aku baru saja mengeluarkan diriku dari wajah. Tapi aku kelewat lelah untuk memedulikan arti semua ini besok pagi. Dalam hitungan detik aku sudah tak sadarkan diri.
Ketika aku terbangun, semua celah di langit-langit kamar di terangi cahaya matahari yang menggema, dan seseorang sedang bersiul.
Siulan itu berhenti.
"Akhirnya," gumam Jeb, ketika mataku terbuka.
Aku berguling sehingga bisa memandangnya. Ketika aku bergerak, tangan Jamie menggelincir dari lenganku. Rupanya semalam ia mengulurkan tangan untuk menggapaiku. Well, bukan menggapaiku, tapi menggapai kakaknya.
Jeb bersandar di ambang pintu batu alami, tangannya terlipat di dada. "Pagi," sapanya. "Cukup tidurnya?"
Aku menggeliat, memutuskan merasa cukup istirahat, lalu mengangguk.
"Oh, jangan membisu lagi," keluh Jeb, memberengut.
"Maaf," gumamku. "Tidurku nyenyak. Terima kasih."
Jamie bergerak mendengar suaraku.
"Wanda?" tanya Jamie.
Dengan tololnya aku merasa terharu, karena ia mengucapkan nama panggilan tololku di pengujung tidurnya.
"Ya?"
Jamie mengerjapkan mata dan menyingkirkan rambut kusutnya.
"Oh, hei, Uncle Jeb."
"Kamarku tidak cukup baik untukmu, Nak?"
"Kau mendengkur sangat keras," ujar Jmaie. Lalu ia menguap.
"Belum pernahkah aku mengajarimu?" tanya Jeb kepadanya. "Sejak kapan kau membiarkan tamu perempuan tidur di lantai?"
Jamie mendadak duduk, menatap sekeliling, kehilangan orientasi. Ia memberengut.
"Jangan membuatnya khawatir," kataku kepada Jeb. "Dia berkeras tidur di kasur gulung. Aku memindahkannya ketika ia sudah terlelap."
Jamie mendengus. "Dulu Mel juga selalu begitu."
Aku sedikit memelototinya, mencoba mengingatkan.
Jeb tergelak. Aku mendongak memandangnya, dan ia memperlihatkan ekspresi kucing menerkam seperti kemarin. Seakan ia telah menemukan jawaban atas teka-tekinya Ia mendekat dan menendang ujung kasur.
"Kau sudah ketinggalan kelas pagimu. Sharon pasti marah soal itu. Ayo, bangun."
"Sharon selalu marah," keluh Jamie, tapi ia cepat-cepat bangkit berdiri.
"Cepat, Nak."
Jamie memandangku lagi, lalu berbalik dan menghilang ke dalam lorong.
"Nah," ujar Jeb, segera setelah kami sendirian. "Kurasa semua omong kosong tentang penjagan ini sudah berlangsung terlalu lama. Aku sibuk. Semua orang sibuk di sini--kelewat sibuk untuk duduk-duduk menjaga. Jadi hari ini kau harus ikut bersamaku, saat aku mengerjakan tugas-tugasku."
Mulutku menganga.
"Jangan kelihatan ketakutan begitu," gerutunya. "Kau akan baik-baik saja." Jeb menepuk-nepuk senapannya. "Rumahku bukan tempat untuk bayi."
Aku tak bisa membantah soal itu. Kuhela napas panjang cepat tiga kali, mencoba menenangkan saraf-sarafku. Darah berdenyut sangat kencang di telingaku, sehingga suara Jeb terdengar pelan ketika ia kembali bicara.
"Ayo, Wanda. Jangan menyia-nyiakan hari."
Jeb berbalik dan keluar dari kamar.
Sejenak aku terpaku, lalu terhuyung-huyung mengikutinya. Jeb tidak menggertak--ia sudah tidak terlihat lagi di belokan pertama. Aku bergegas mengejarnya, ngeri membayangkan akan berjumpa orang lain di bagian yang jelas tak berpenghuni ini. Aku menyusul Jeb sebelum ia tiba di persimpangan besar terowongan. Ia bahkan tidak memandangku, ketika aku memperlambat langkah di sampingnya untuk mengimbanginya.
"Sudah saatnya ladang timur laut ditanami. Kita harus menggarap tanahnya dulu. Kuharap kau tidak keberatan mengotori tanganmu. Setelah selesai akan kupastikan kau punya kesempatan untuk mandi. Kau membutuhkannya." Jeb sengaja mengendus-endus, lalu tertawa.
Kurasakan tengkukku memerah, tapi kuabaikan kalimat terakhir itu. "Aku tidak keberatan mengotori tanganku," gumamku. Ketika kuingat-ingat, ladang timur laut kosong itu terpencil letaknya. Mungkin kami bisa bekerja sendirian.
Setelah tiba di plaza utama, kami mulai melewati para manusia. Mereka menatap marah seperti biasa. Aku mulai mengenali sebagian besar. Ada perempuan setengah baya berambut hitam keabu-abuan panjang dikepang yang kulihat bersama tim irigasi kemarin. Lalu lelaki pendek berperut bulat, berambut pirang menipis dan berpipi kemerahan yang ada bersama perempuan tadi. Perempuan yang tampak atletis dengan kulit cokelat karamel adalah orang yang membungkuk mengikat tali sepatu ketika pertama kali aku kemari di siang hari. Perempuan berkulit gelap lain, dengan bibir tebal dan mata mengantuk, berada di dapur waktu itu, di dekat dua anak kecil berambut hitam. Mungkinkah perempuan itu ibu mereka? Kini kami melewati maggie. Ia memelototi Jeb dan memalingkan wajah dariku. Kami melewati lelaki pucat berambut putih yang tampak kurang sehat, yang pasti tak pernah kulihat sebelumnya. lalu kami melewati Ian.
"Hei, Jeb," sapa Ian ceria. "Mau ke mana?"
"Membalik tanah di ladang timur, gerutu Jeb.
"Perlu bantuan?"
"Harus membuat dirimu berguna," gumam Jeb.
Ian menganggap ini sebagai persetujuan, lalu mengikuti di belakangku. Aku merinding merasakan matanya memandang punggungku.
Kami melewati seorang pemuda, yang mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari Jamie, dengan rambut warna gelap mencuat dari kening warna zaitunnya, seperti wol baja.
"Hei, Wes," sapa Ian.
Wes mengamati ketika kami melewatinya. Ian tertawa melihat ekspresinya.
Kami melewati Doc.
"Hei, Doc," sapa Ian.
"Ian." Doc mengangguk. Di tangannya ada gumpalan besar adonan. Kemejanya dikotori tepung kasar warna gelap. "Pagi, Jeb. Pagi, Wanda."
"Pagi," jawab Jeb.
Aku mengangguk tidak nyaman.
"Sampai jumpa," ujar Doc, bergegas pergi membawa adonannya.
"Wanda, heh?" tanya Ian.
"Ideku," ujar Jeb. "Kurasa occok untuknya."
"Menarik." Hanya itu yang dikatakan Ian.
Akhirnya kami sampai di ladang timur laut, tempat harapan-harapanku hancur.
Lebih banyak orang di sini daripada di lorong-lorong. Lima perempuan dan sembilan laki-laki. Mereka berhenti bekerja dan, tentu saja, memberengut.
"Jangan pedulikan mereka," gumam Jeb.
Jeb mengikuti sarannya sendiri; ia pergi ke tumpukan peralatan yang tersandar di dinding terdekat, menyelipkan senapan ke pinggang, lalu meraih cangkul dan dua sekop.
Dengan jeb begitu jauh, aku merasa diriku jelas terlihat. Ian hanya selangkah di belakang. Bisa kudengar suara napasnya. Yang lain terus menatap marah, dengan peralatan di tangan masing-masing. Aku tidak melewatkan fakta bahwa cangkul yang digunakan untuk menghancurkan tanah bisa dengan mudah digunakan untuk menghancurkan tubuh. Saat membaca beberapa ekspresi mereka, bagiku tampaknya bukan hanya diriku yang punya gagasan semacam itu.
Jeb kembali dan memberiku sekop. Aku mencengkeram pegangan kayunya yang aus dan licin, merasakan bobotnya. Setelah melihat pandangan haus darah di mata manusia-manusia itu, sulit bagiku untuk tidak menganggap sekop itu senjata. Aku tidak menyukai gagasan itu. Aku ragu, apakah bisa mengangkat benda itu sebagai senjata, bahkan untuk menghalangi pukulan saja.
Jeb memberikan cangkulnya kepada Ian. Logam tajam menghitam itu tampak mematikan di tangannya. Perlu segenap tekad agar aku tidak menyelinap keluar dari jangkauannya.
"Ayo menggarap pojok belakang."
Setidaknya Jeb membawaku ke tempat yang paling tidak ramai di gua panjang terang itu. Ia menyuruh Ian menghancurkan tanah yang mengeras terpanggang matahari di depan kami, sementara aku menggemburkan bongkah-bongkah tanah itu. Jeb mengikuti di belakangku, dengan pinggiran sekop ia menghancurkan bongkahan-bongkahan itu menjadi tanah yang berguna.
Ketika melihat keringat yang mengaliri kulit putih Ian--ia melepaskan kemeja setelah beberapa detik terbakar cahaya cermin--dan mendengar napas tersengal-sengal Jeb di belakangku, kusadari aku mendapat pekerjaan termudah. Aku berharap diharuskan melakukan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang akan membuatku tidak terganggu oleh gerakan manusia-manusia lain. Setiap gerakan mereka membuatku tersentak dan menciut.
Aku tak bisa melakukkan pekerjaan Ian. Aku tidak punya lengan kekar dan otot-otot punggung yang dibutuhkan untuk benar-benar menghancurkan tanah keras. Tapi kuputuskan untuk melakukan pekerjaan Jeb sebisa mungkin. Kuhancurkan bongkahan-bongkahan itu sampai kecil-kecil sebelum bergerak maju. Pekerjaan itu sedikit membantu--membuat mataku sibuk dan sangat melelahkan sehingga aku harus berkonsentrasi untuk membuat diriku terus bekerja.
Sesekali Ian membawakan air. Ada perempuan--pendek putih, aku melihatnya di dapur kemarin--yang tampaknya bertugas membawakan air untuk yang lain. Tapi ia mengabaikan kami. Ian selalu membawa cukup air untuk kami bertiga. Aku cemas mellihat perubahan sikapnya mengenai diriku. Apakah Ian benar-benar tak lagi menginginkan kematianku? Ataukah ia hanya mencari kesempatan? Air selalu aneh rasanya di sini--apak dan bersulfur--tapi kini rasanya mencurigakan. Kucoba mengabaikan pikiran sinting itu sebisa mungkin.
Aku bekerja cukup keras untuk menyibukkan mata dan membekukan pikiran; aku tidak memperhatikan ketika kami tiba di ujung baris terakhir. Aku baru berhenti ketika Ian berhenti. Ia menggeliat, mengangkat cangkul ke atas kepala dengan dua tangan, lalu mengertakkan semua persendiaan tubuhnya. Aku menjauhi cangkul yang terangkat itu, tapi Ian tidak memperhatikan. Kusadari semua orang sudah berhenti bekerja. Aku memandang tanah yang baru saja digemburkan, bahkan memandang seluruh lantai, dan kusadari ladangnya sudah selesai digarap.
"Kerja kalian bagus," Jeb mengumumkan dengan suara lantang. "Kita akan menanam dan mengairinya besok."
Ruangan dipenuhi celotehan pelan dan bunyi berdentang ketika semua peralatan kembali ditumpuk menyandar di dinding. Beberapa percakapan terdengar santai; beberapa masih tegang karena kehadiranku. Ian mengulurkan tangan meminta sekopku, dan kuserahkan benda itu kepadanya, lalu kurasakan suasana hatiku ang lesu seakan tenggelam ke lantai. Tak diragukan lagi aku termasuk dalam kata "kita" yang diucapkan Jeb. Besok pasti sama sulitnya seperti hari ini.
Dengan sedih aku memandang Jeb, dan ia tersenyum. Ada perasaan bangga dalam seringai Jeb, yang membuatku percaya ia tahu apa yang kupikirkan. Ia tidak hanya menebak ketidaknyamananku, tapi juga menikmatinya.
Jeb, teman sintingku, mengedipkan sebelah mata. Kembali kusadari inilah hal terbaik yang bisa diharapkan dari persahabatan manusia.
"Sampai besok, Wanda," seru Ian dari seberang ruangan, lalu tertawa sendiri.
Semua menatapnya.
Jual Nugget dan Sosis Sayur

Pemesanan via email : lwati111@gmail.com
The Host - Bab 23
Mengaku
Bayangan itu besar dan aneh bentuknya, menjulang di atas tubuhku, sangat berat, dan berayun mendekati wajahku.
Kurasa aku hendak berteriak, tapi teriakanku terperangkap di dalam tenggorokan, dan yang keluar hanya decit pelan.
"Sst, ini aku," bisik Jamie. Sesuatu yang besar dan bulat berguling dari bahunya dan berdebum pelan ke lantai. Ketika benda itu lenyap, aku bisa melihat bayangan kecil Jamie yang sebenarnya, dilatari cahaya bulan.
Sejenak aku tersengal, tanganku mencengkeram leher.
"Maaf," bisik Jamie. Ia duduk di tepi kasur. "Kurasa perbuatanku sangat tolol. Aku berusaha untuk tidak membangunkan Doc. Aku bahkan tidak berpikir, betapa aku akan membuatmu ketakutan. Kau baik-baik saja?" Ia menepuk-nepuk pergelangan kakiku-bagian tubuhku yang terdekat dengannya.
"Tentu," ujarku, masih tersengal.
"Maaf," gumamnya lagi.
"Apa yang kaulakukan di sini, Jamie? Bukankah kau seharusnya tidur?"
"Itulah sebabnya aku di sini. Uncle Jeb mendengkur keras sekali, sehingga kau mungkin takkan percaya. Aku tidak tahan lagi."
Jawaban Jamie tak masuk akal. "Bukankah kau biasa tidur bersama Jeb?"
Jamie menguap, lalu membungkuk untuk membuka pengikat kasur gulung besar yang tadi dijatuhkannya ke lantai. "Tidak, aku biasanya tidur bersama Jared. Ia tidak mendengkur. Tapi kau sudah tahu itu."
Memang.
"Lalu mengapa kau tidak tidur di kamar Jared? Kau takut tidur sendirian?" Aku takkan menyalahkannya untuk itu. Tampaknya di sini selalu menakutkan.
"Takut?" Jamie menggerutu, tersinggung. "Tidak. Ini kamar Jared. Dan kamarku."
"Apa?" aku terkesiap. "Jeb menempatkanku di kamar Jared?"
Aku tidak percaya ini. Jared akan membunuhku. Tidak, ia akan membunuh Jeb lebih dulu, lalu membunuhku.
"Ini kamarku juga. Dan kubilang pada Jeb, kau bisa memakainya."
"Jared akan marah besar," bisikku.
"Aku bisa melakukan apa pun yang kuinginkan dengan kamarku," bantah Jamie, tapi ia lalu menggigit bibir. "Kita tidak akan memberitahunya. Jared tak perlu tahu."
Aku mengangguk. "Ide bagus."
"Kau tidak keberatan aku tidur di sini, kan? Uncle Jeb benar-benar berisik."
"Tidak. Aku tidak keberatan. Tapi, Jamie, kurasa kau tidak boleh melakukannya."
Jamie memberengut, mencoba tampak tegar, bukannya terluka.
"Kenapa tidak?"
"Karena tidak aman. Terkadang orang datang mencariku di malam hari."
Matanya membelalak. "Benarkah?"
"Jared selalu memegang senapan--sehingga mereka pergi."
"Siapa?"
"Aku tak tahu--kadang-kadang Kyle. Tapi pasti masih ada orang-orang lain yang berada di sini."
Jamie mengangguk. "Lebih banyak lagi alasan mengapa aku harus tetap di sini. Doc mungkn perlu bantuan."
"Jamie--"
"Aku bukan anak-anak, Wanda. Aku bisa menjaga diriku sendiri."
Membantah jelas hanya akan membuat Jamie semakin keras kepala. "Setidaknya, pakailah tempat tidurnya," ujarku menyerah.
"Aku akan tidur di lantai. Ini kamarmu."
"Itu keliru. Kau tamu."
Aku mendengus pelan. "Ha. Tidak, tempat tidurnya untukmu."
"Tak mungkin." Jamie berbaring di kasur gulung, lalu melipat kedua lengannya rapat-rapat di dada.
Sekali lagi aku melihat membantah adalah pendekatan yang keliru untuk Jamie. Well, yang ini bisa langsung kuperbaiki setelah ia tidur. Jamie tidur sangat nyenyak, sampai nyaris bisa disebut koma. Melanie duku bisa menggendongnya ke mana pun setelah ia tertidur.
"Kau bisa memakai bantalku," kata Jamie kepadaku, seraya menepuk-nepuk bantal di sebelah tempatnya berbaring. "Kau tak perlu meringkuk di ujung sana."
Aku mendesah, tapi merangkak ke bagian atas tempat tidur.
"Nah, begitu," ujarnya setuju. "Sekarang, bisakah kau melemparkan bantal Jared kepadaku?"
Aku bimbang, hendak meraih bantal di bawah kepalaku. Jamie melompat bangun, membungkuk ke arahku, lalu meraih bantal yang lain. Aku kembali mendesah.
Sejenak kami berbaring dalam keheningan, mendengarkan siulan rendah napas Doc.
"Dengkuran Doc menyenangkan, bukan?" bisik Jamie.
"Tidak membuatmu terjaga," jawabku mengiyakan.
"Kau lelah?"
"Ya."
"Oh."
Aku menunggu Jamie mengatakan sesuatu lagi, tapi ia diam saja.
"Ada sesuatu yang kauinginkan?" tanyaku.
Jamie tidak langsung menjawab, tapi bisa kurasakan pergulatannya, jadi aku menunggu.
"Kalau aku menanyakan sesuatu, maukah kau mengatakan yang sebenarnya?"
Giliranku bimbang. "Aku tidak mengetahui semua hal," elakku.
"Yang ini kau pasti tahu. Ketika kami sedang berjalan... aku dan Jeb... dia menceritakan beberapa hal. Hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Tapi aku tak tahu apakah dia benar."
Mendadak melanie sangat hadir di dalam kepalaku.
Bisikan Jamie sulit didengar, lebih pelan daripada napasku. "Menurut Uncle Jeb, Melanie mungkin masih hidup. Maksudku, dia berada di dalam sana bersamamu."
Jamie-ku. Melanie mendesah.
Aku tak menjawab keduanya.
"Aku tak tahu apakah itu bisa terjadi. Apakah itu terjadi?" Suara Jamie pecah, dan aku bisa mendengar ia memerangi air mata. Ia bukan anak cengeng, dan aku kembali sangat sedih untuknya, dua kali dalam satu hari. Perasaan nyeri menembus dadaku.
"Benarkah, Wanda?"
Katakan kepadanya. Kumohon, katakan aku mencintainya.
"Kenapa kau tidak mau menjawabku?" Kini jamie benar-benar menangis, tapi ia mencoba meredam suaranya.
Aku merangkak turun dari tempat tidur, lalu menjejalkan diri ke celah keras di antara tempat tidur dan kasur gulung, mengulurkan tangan ke dada Jamie yang bergetar. Kusurukkan kepalaku ke rambutnya, dan kurasakan air matanya, hangat di leherku.
"Apakah Melanie masih hidup, Wanda? Kumohon?"
Mungkin Jamie hanyalah alat. Lelaki tua itu bisa saja mengutus Jamie khusus untuk ini; Jeb cukup pintar untuk melihat betapa mudah Jamie mematahkan pertahananku. Mungkin Jeb mencari penegasan atas teorinya, dan ia tak segan-segan menggunakan anak ini untuk mendapatkannya. Apa yang akan ia perbuat, ketika meyakini kebenaran berbahaya itu? Bagaimana ia akan menggunakan informasi itu? Kurasa ia tidak bermaksud jahat, tapi bisakah aku memercayai penilaianku sendiri? Manusia adalah mahluk penipu, pengkhianat. Aku tak bisa mengantisipasi niat mereka yang lebih kelam, karena hal-hal semacam itu tak terpikirkan oleh spesiesku.
Tubuh Jamie berguncang-guncang di sampingku.
Ia menderita, teriak Melanie. Sia-sia Melanie melawan kendaliku.
Tapi aku tak bisa menyalahkan Melanie, seandainya ini ternyata merupakan kesalahan besar. Aku tahu siapa yang kini sedang bicara.
"Melanie berjanji akan kembali, bukan?" gumamku. "Akankah dia mengingkari janjinya kepadamu?"
Jamie melingkarkan kedua tangannya di pinggangku dan menggayutiku untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit ia berbisik, "Aku sayang padamu, Mel."
"Dia sayang padamu juga. Dia sangat senang kau ada di sini dan aman."
Jamie diam cukup lama sehingga air mata di kulitku mengering, meninggalkan debu asin halus.
"Apakah semua orang seperti itu?" bisik Jamie, lama setelah aku mengira ia telah terlelap. "Apakah semua orang tetap tinggal di dalam sana?"
"Tidak," ujarku sedih. "Tidak. Melanie istimewa."
"Dia kuat dan berani."
"Sangat."
"Apakah menurutmu..." Jamie berhenti untuk menghela napas. "Apakah menurutmu Dad mungkin masih berada di sana juga?"
Aku menelan ludah, mencoba mendorong gumpalan itu lebih jauh ke dalam tenggorokan. Sia-sia. "Tidak, Jamie. Tidak, kurasa tidak. Tidak seperti Melanie."
"Kenapa?"
"Karena ayahmu membawa para Pencari untuk menangkapmu. Well, jiwa di dalamnya yang melakukan itu. Ayahmu takkan membiarkan itu terjadi, kalau saja dia masih di sana. Melanie tak pernah membiarkanku melihat di mana kabin itu berada. Dan untuk waktu yang lama sekali, dia bahkan tidak membiarkanku tahu kau ada. Dia tidak membawaku kemari, sampai merasa yakin aku takkan melukaimu."
Terlalu banyak informasi. Selesai bicara, baru kusadari Doc tak lagi mendengkur. Aku tidak bisa mendengar suara napasnya. Tolol. Diam-diam kumaki diriku sendiri.
"Wow," ujar Jamie.
Aku berbisik di telinganya, begitu dekat sehingga tak mungkin Doc bisa menguping. "Ya, Melanie sangat kuat."
Jamie berusaha keras mendengarku. Ia cemberut, lalu melirik lubang menuju lorong gelap. Ia menyadari hal yang sama, karena ia mengarahkan wajah ke telingaku dan kembali berbisik, lebih pelan daripada sebelumnya. "Mengapa kau bersedia melakukannya? Tidak melukai kami? Bukankah itu yang kauinginkan?"
"Tidak. Aku tidak ingin melukaimu."
"Mengapa?"
"Aku dan kakakmu telah... menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Dia membagimu untuk kami berdua. Dan... aku mulai... sayang padamu juga."
"Dan Jared juga?"
Sejenak aku menggertakkan gigi, merasa kesal karena dengan mudah Jamie bisa menghubungkan kedua hal itu. "Tentu saja aku juga tak menginginkan apa pun melukai Jared."
"Jared membencimu," ujar Jamie. Jelas ia sedih melihat kenyataan itu.
"Ya. Semua orang membenciku." Aku mendesah. "Aku tak bisa menyalahkan mereka."
"Jeb tidak membencimu. Aku juga."
"Kau mungkin akan membenciku, setelah lebih banyak merenungkannya."
"Tapi kau bahkan tidak berada di sini ketika mereka mengambil alih. Kau tidak memilih ayahku atau ibuku atau Melanie. Saat itu kau berada di luar angkasa, bukan?"
"Ya, tapi aku adalah aku, Jamie. Aku melakukan apa yang dilakukan jiwa. Aku punya banyak inang sebelum Melanie, dan tak ada yang menghentikanku untuk... merampas kehidupan. Berulang kali. Begitulah cara hidupku."
"Apakah Melanie membencimu?"
Sejenak aku berpikir. "Dia tidak terlalu membenciku seperti dulu."
Tidak. Aku sama sekali tidak membencimu. Tidak lagi.
"Katanya dia sama sekali tak membenciku," gumamku, nyaris tak terdengar.
"Bagaimana... bagaimana kabarnya?
"Dia senang berada di sini. Dia begitu bahagia berjumpa denganmu. Dia bahkan tak peduli apakah mereka hendak membunuh kami."
Jamie mengejang di bawah lenganku. "Mereka tidak bisa membunuhmu! Tidak bisa, jika Mel masih hidup!"
Kau membuatnya sedih, keluh Melanie. Kau tidak perlu berkata begitu.
Tidak bakal mudah baginya, kalau ia tidak siap.
"Mereka takkan percaya itu, Jamie," bisikku. "Mereka akan mengira aku berbohong untuk menipumu. Kalau kau menceritakan hal ini, mereka hanya akan semakin bernafsu membunuhku. Hanya Pencari yang berbohong."
Kata itu membuat Jamie bergidik.
"Tapi kau tidak bohong. Aku tahu itu," ujar Jamie setelah beberapa saat.
Aku mengangkat bahu.
"Aku takkan membiarkan mereka membunuh Mel."
Suara Jamie, walaupun sepelan napas, terdengar garang penuh tekad. Aku terpaku, membayangkan dirinya semakin terlibat dengan situasi ini, semakin terlibat denganku. Kubayangkan orang-orang barbar yang tinggal bersamanya. Apakah usia muda akan melindungi Jamie dari mereka, seandainya ia mencoba melindungiku? Aku ragu. Pikiranku campur aduk, mencari cara untuk mencegah Jamie tanpa memicu kekeraskepalaannya.
Jamie bicara sebelum aku bisa mengatakan sesuatu; mendadak ia berubah tenang, seolah jawabannya sudah jelas di depannya. "Jared akan memikirkan sesuatu. Dia selalu begitu."
"Jared juga tidak bakal percaya. Dia akan menjadi yang paling marah di antara mereka semua."
"Bahkan seandainya tidak percaya, dia akan melindungi Mel, sekadar berjaga-jaga."
"Akan kita lihat nanti," gumamku. Nanti akan kucari kata-kata yang sempurna--bantahan yang tidak akan terdengar seperti bantahan.
Jamie diam, berpikir. Akhirnya napasnya melambat dan mulutnya terbuka. Aku menunggu sampai yakin ia sudah tidur nyenyak, lalu aku menghampirinya, dan dengan sangat hati-hati memindahkannya dari lantai ke tempat tidur. Ia lebih berat daripada dulu, tapi aku berhasil. Ia tidak terbangun.
Kuletakkan bantal Jared di tempatnya, lalu kurebahkan tubuhku ke atas kasur gulung.
Well, pikirku. Aku baru saja mengeluarkan diriku dari wajah. Tapi aku kelewat lelah untuk memedulikan arti semua ini besok pagi. Dalam hitungan detik aku sudah tak sadarkan diri.
Ketika aku terbangun, semua celah di langit-langit kamar di terangi cahaya matahari yang menggema, dan seseorang sedang bersiul.
Siulan itu berhenti.
"Akhirnya," gumam Jeb, ketika mataku terbuka.
Aku berguling sehingga bisa memandangnya. Ketika aku bergerak, tangan Jamie menggelincir dari lenganku. Rupanya semalam ia mengulurkan tangan untuk menggapaiku. Well, bukan menggapaiku, tapi menggapai kakaknya.
Jeb bersandar di ambang pintu batu alami, tangannya terlipat di dada. "Pagi," sapanya. "Cukup tidurnya?"
Aku menggeliat, memutuskan merasa cukup istirahat, lalu mengangguk.
"Oh, jangan membisu lagi," keluh Jeb, memberengut.
"Maaf," gumamku. "Tidurku nyenyak. Terima kasih."
Jamie bergerak mendengar suaraku.
"Wanda?" tanya Jamie.
Dengan tololnya aku merasa terharu, karena ia mengucapkan nama panggilan tololku di pengujung tidurnya.
"Ya?"
Jamie mengerjapkan mata dan menyingkirkan rambut kusutnya.
"Oh, hei, Uncle Jeb."
"Kamarku tidak cukup baik untukmu, Nak?"
"Kau mendengkur sangat keras," ujar Jmaie. Lalu ia menguap.
"Belum pernahkah aku mengajarimu?" tanya Jeb kepadanya. "Sejak kapan kau membiarkan tamu perempuan tidur di lantai?"
Jamie mendadak duduk, menatap sekeliling, kehilangan orientasi. Ia memberengut.
"Jangan membuatnya khawatir," kataku kepada Jeb. "Dia berkeras tidur di kasur gulung. Aku memindahkannya ketika ia sudah terlelap."
Jamie mendengus. "Dulu Mel juga selalu begitu."
Aku sedikit memelototinya, mencoba mengingatkan.
Jeb tergelak. Aku mendongak memandangnya, dan ia memperlihatkan ekspresi kucing menerkam seperti kemarin. Seakan ia telah menemukan jawaban atas teka-tekinya Ia mendekat dan menendang ujung kasur.
"Kau sudah ketinggalan kelas pagimu. Sharon pasti marah soal itu. Ayo, bangun."
"Sharon selalu marah," keluh Jamie, tapi ia cepat-cepat bangkit berdiri.
"Cepat, Nak."
Jamie memandangku lagi, lalu berbalik dan menghilang ke dalam lorong.
"Nah," ujar Jeb, segera setelah kami sendirian. "Kurasa semua omong kosong tentang penjagan ini sudah berlangsung terlalu lama. Aku sibuk. Semua orang sibuk di sini--kelewat sibuk untuk duduk-duduk menjaga. Jadi hari ini kau harus ikut bersamaku, saat aku mengerjakan tugas-tugasku."
Mulutku menganga.
"Jangan kelihatan ketakutan begitu," gerutunya. "Kau akan baik-baik saja." Jeb menepuk-nepuk senapannya. "Rumahku bukan tempat untuk bayi."
Aku tak bisa membantah soal itu. Kuhela napas panjang cepat tiga kali, mencoba menenangkan saraf-sarafku. Darah berdenyut sangat kencang di telingaku, sehingga suara Jeb terdengar pelan ketika ia kembali bicara.
"Ayo, Wanda. Jangan menyia-nyiakan hari."
Jeb berbalik dan keluar dari kamar.
Sejenak aku terpaku, lalu terhuyung-huyung mengikutinya. Jeb tidak menggertak--ia sudah tidak terlihat lagi di belokan pertama. Aku bergegas mengejarnya, ngeri membayangkan akan berjumpa orang lain di bagian yang jelas tak berpenghuni ini. Aku menyusul Jeb sebelum ia tiba di persimpangan besar terowongan. Ia bahkan tidak memandangku, ketika aku memperlambat langkah di sampingnya untuk mengimbanginya.
"Sudah saatnya ladang timur laut ditanami. Kita harus menggarap tanahnya dulu. Kuharap kau tidak keberatan mengotori tanganmu. Setelah selesai akan kupastikan kau punya kesempatan untuk mandi. Kau membutuhkannya." Jeb sengaja mengendus-endus, lalu tertawa.
Kurasakan tengkukku memerah, tapi kuabaikan kalimat terakhir itu. "Aku tidak keberatan mengotori tanganku," gumamku. Ketika kuingat-ingat, ladang timur laut kosong itu terpencil letaknya. Mungkin kami bisa bekerja sendirian.
Setelah tiba di plaza utama, kami mulai melewati para manusia. Mereka menatap marah seperti biasa. Aku mulai mengenali sebagian besar. Ada perempuan setengah baya berambut hitam keabu-abuan panjang dikepang yang kulihat bersama tim irigasi kemarin. Lalu lelaki pendek berperut bulat, berambut pirang menipis dan berpipi kemerahan yang ada bersama perempuan tadi. Perempuan yang tampak atletis dengan kulit cokelat karamel adalah orang yang membungkuk mengikat tali sepatu ketika pertama kali aku kemari di siang hari. Perempuan berkulit gelap lain, dengan bibir tebal dan mata mengantuk, berada di dapur waktu itu, di dekat dua anak kecil berambut hitam. Mungkinkah perempuan itu ibu mereka? Kini kami melewati maggie. Ia memelototi Jeb dan memalingkan wajah dariku. Kami melewati lelaki pucat berambut putih yang tampak kurang sehat, yang pasti tak pernah kulihat sebelumnya. lalu kami melewati Ian.
"Hei, Jeb," sapa Ian ceria. "Mau ke mana?"
"Membalik tanah di ladang timur, gerutu Jeb.
"Perlu bantuan?"
"Harus membuat dirimu berguna," gumam Jeb.
Ian menganggap ini sebagai persetujuan, lalu mengikuti di belakangku. Aku merinding merasakan matanya memandang punggungku.
Kami melewati seorang pemuda, yang mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari Jamie, dengan rambut warna gelap mencuat dari kening warna zaitunnya, seperti wol baja.
"Hei, Wes," sapa Ian.
Wes mengamati ketika kami melewatinya. Ian tertawa melihat ekspresinya.
Kami melewati Doc.
"Hei, Doc," sapa Ian.
"Ian." Doc mengangguk. Di tangannya ada gumpalan besar adonan. Kemejanya dikotori tepung kasar warna gelap. "Pagi, Jeb. Pagi, Wanda."
"Pagi," jawab Jeb.
Aku mengangguk tidak nyaman.
"Sampai jumpa," ujar Doc, bergegas pergi membawa adonannya.
"Wanda, heh?" tanya Ian.
"Ideku," ujar Jeb. "Kurasa occok untuknya."
"Menarik." Hanya itu yang dikatakan Ian.
Akhirnya kami sampai di ladang timur laut, tempat harapan-harapanku hancur.
Lebih banyak orang di sini daripada di lorong-lorong. Lima perempuan dan sembilan laki-laki. Mereka berhenti bekerja dan, tentu saja, memberengut.
"Jangan pedulikan mereka," gumam Jeb.
Jeb mengikuti sarannya sendiri; ia pergi ke tumpukan peralatan yang tersandar di dinding terdekat, menyelipkan senapan ke pinggang, lalu meraih cangkul dan dua sekop.
Dengan jeb begitu jauh, aku merasa diriku jelas terlihat. Ian hanya selangkah di belakang. Bisa kudengar suara napasnya. Yang lain terus menatap marah, dengan peralatan di tangan masing-masing. Aku tidak melewatkan fakta bahwa cangkul yang digunakan untuk menghancurkan tanah bisa dengan mudah digunakan untuk menghancurkan tubuh. Saat membaca beberapa ekspresi mereka, bagiku tampaknya bukan hanya diriku yang punya gagasan semacam itu.
Jeb kembali dan memberiku sekop. Aku mencengkeram pegangan kayunya yang aus dan licin, merasakan bobotnya. Setelah melihat pandangan haus darah di mata manusia-manusia itu, sulit bagiku untuk tidak menganggap sekop itu senjata. Aku tidak menyukai gagasan itu. Aku ragu, apakah bisa mengangkat benda itu sebagai senjata, bahkan untuk menghalangi pukulan saja.
Jeb memberikan cangkulnya kepada Ian. Logam tajam menghitam itu tampak mematikan di tangannya. Perlu segenap tekad agar aku tidak menyelinap keluar dari jangkauannya.
"Ayo menggarap pojok belakang."
Setidaknya Jeb membawaku ke tempat yang paling tidak ramai di gua panjang terang itu. Ia menyuruh Ian menghancurkan tanah yang mengeras terpanggang matahari di depan kami, sementara aku menggemburkan bongkah-bongkah tanah itu. Jeb mengikuti di belakangku, dengan pinggiran sekop ia menghancurkan bongkahan-bongkahan itu menjadi tanah yang berguna.
Ketika melihat keringat yang mengaliri kulit putih Ian--ia melepaskan kemeja setelah beberapa detik terbakar cahaya cermin--dan mendengar napas tersengal-sengal Jeb di belakangku, kusadari aku mendapat pekerjaan termudah. Aku berharap diharuskan melakukan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang akan membuatku tidak terganggu oleh gerakan manusia-manusia lain. Setiap gerakan mereka membuatku tersentak dan menciut.
Aku tak bisa melakukkan pekerjaan Ian. Aku tidak punya lengan kekar dan otot-otot punggung yang dibutuhkan untuk benar-benar menghancurkan tanah keras. Tapi kuputuskan untuk melakukan pekerjaan Jeb sebisa mungkin. Kuhancurkan bongkahan-bongkahan itu sampai kecil-kecil sebelum bergerak maju. Pekerjaan itu sedikit membantu--membuat mataku sibuk dan sangat melelahkan sehingga aku harus berkonsentrasi untuk membuat diriku terus bekerja.
Sesekali Ian membawakan air. Ada perempuan--pendek putih, aku melihatnya di dapur kemarin--yang tampaknya bertugas membawakan air untuk yang lain. Tapi ia mengabaikan kami. Ian selalu membawa cukup air untuk kami bertiga. Aku cemas mellihat perubahan sikapnya mengenai diriku. Apakah Ian benar-benar tak lagi menginginkan kematianku? Ataukah ia hanya mencari kesempatan? Air selalu aneh rasanya di sini--apak dan bersulfur--tapi kini rasanya mencurigakan. Kucoba mengabaikan pikiran sinting itu sebisa mungkin.
Aku bekerja cukup keras untuk menyibukkan mata dan membekukan pikiran; aku tidak memperhatikan ketika kami tiba di ujung baris terakhir. Aku baru berhenti ketika Ian berhenti. Ia menggeliat, mengangkat cangkul ke atas kepala dengan dua tangan, lalu mengertakkan semua persendiaan tubuhnya. Aku menjauhi cangkul yang terangkat itu, tapi Ian tidak memperhatikan. Kusadari semua orang sudah berhenti bekerja. Aku memandang tanah yang baru saja digemburkan, bahkan memandang seluruh lantai, dan kusadari ladangnya sudah selesai digarap.
"Kerja kalian bagus," Jeb mengumumkan dengan suara lantang. "Kita akan menanam dan mengairinya besok."
Ruangan dipenuhi celotehan pelan dan bunyi berdentang ketika semua peralatan kembali ditumpuk menyandar di dinding. Beberapa percakapan terdengar santai; beberapa masih tegang karena kehadiranku. Ian mengulurkan tangan meminta sekopku, dan kuserahkan benda itu kepadanya, lalu kurasakan suasana hatiku ang lesu seakan tenggelam ke lantai. Tak diragukan lagi aku termasuk dalam kata "kita" yang diucapkan Jeb. Besok pasti sama sulitnya seperti hari ini.
Dengan sedih aku memandang Jeb, dan ia tersenyum. Ada perasaan bangga dalam seringai Jeb, yang membuatku percaya ia tahu apa yang kupikirkan. Ia tidak hanya menebak ketidaknyamananku, tapi juga menikmatinya.
Jeb, teman sintingku, mengedipkan sebelah mata. Kembali kusadari inilah hal terbaik yang bisa diharapkan dari persahabatan manusia.
"Sampai besok, Wanda," seru Ian dari seberang ruangan, lalu tertawa sendiri.
Semua menatapnya.
Bayangan itu besar dan aneh bentuknya, menjulang di atas tubuhku, sangat berat, dan berayun mendekati wajahku.
Kurasa aku hendak berteriak, tapi teriakanku terperangkap di dalam tenggorokan, dan yang keluar hanya decit pelan.
"Sst, ini aku," bisik Jamie. Sesuatu yang besar dan bulat berguling dari bahunya dan berdebum pelan ke lantai. Ketika benda itu lenyap, aku bisa melihat bayangan kecil Jamie yang sebenarnya, dilatari cahaya bulan.
Sejenak aku tersengal, tanganku mencengkeram leher.
"Maaf," bisik Jamie. Ia duduk di tepi kasur. "Kurasa perbuatanku sangat tolol. Aku berusaha untuk tidak membangunkan Doc. Aku bahkan tidak berpikir, betapa aku akan membuatmu ketakutan. Kau baik-baik saja?" Ia menepuk-nepuk pergelangan kakiku-bagian tubuhku yang terdekat dengannya.
"Tentu," ujarku, masih tersengal.
"Maaf," gumamnya lagi.
"Apa yang kaulakukan di sini, Jamie? Bukankah kau seharusnya tidur?"
"Itulah sebabnya aku di sini. Uncle Jeb mendengkur keras sekali, sehingga kau mungkin takkan percaya. Aku tidak tahan lagi."
Jawaban Jamie tak masuk akal. "Bukankah kau biasa tidur bersama Jeb?"
Jamie menguap, lalu membungkuk untuk membuka pengikat kasur gulung besar yang tadi dijatuhkannya ke lantai. "Tidak, aku biasanya tidur bersama Jared. Ia tidak mendengkur. Tapi kau sudah tahu itu."
Memang.
"Lalu mengapa kau tidak tidur di kamar Jared? Kau takut tidur sendirian?" Aku takkan menyalahkannya untuk itu. Tampaknya di sini selalu menakutkan.
"Takut?" Jamie menggerutu, tersinggung. "Tidak. Ini kamar Jared. Dan kamarku."
"Apa?" aku terkesiap. "Jeb menempatkanku di kamar Jared?"
Aku tidak percaya ini. Jared akan membunuhku. Tidak, ia akan membunuh Jeb lebih dulu, lalu membunuhku.
"Ini kamarku juga. Dan kubilang pada Jeb, kau bisa memakainya."
"Jared akan marah besar," bisikku.
"Aku bisa melakukan apa pun yang kuinginkan dengan kamarku," bantah Jamie, tapi ia lalu menggigit bibir. "Kita tidak akan memberitahunya. Jared tak perlu tahu."
Aku mengangguk. "Ide bagus."
"Kau tidak keberatan aku tidur di sini, kan? Uncle Jeb benar-benar berisik."
"Tidak. Aku tidak keberatan. Tapi, Jamie, kurasa kau tidak boleh melakukannya."
Jamie memberengut, mencoba tampak tegar, bukannya terluka.
"Kenapa tidak?"
"Karena tidak aman. Terkadang orang datang mencariku di malam hari."
Matanya membelalak. "Benarkah?"
"Jared selalu memegang senapan--sehingga mereka pergi."
"Siapa?"
"Aku tak tahu--kadang-kadang Kyle. Tapi pasti masih ada orang-orang lain yang berada di sini."
Jamie mengangguk. "Lebih banyak lagi alasan mengapa aku harus tetap di sini. Doc mungkn perlu bantuan."
"Jamie--"
"Aku bukan anak-anak, Wanda. Aku bisa menjaga diriku sendiri."
Membantah jelas hanya akan membuat Jamie semakin keras kepala. "Setidaknya, pakailah tempat tidurnya," ujarku menyerah.
"Aku akan tidur di lantai. Ini kamarmu."
"Itu keliru. Kau tamu."
Aku mendengus pelan. "Ha. Tidak, tempat tidurnya untukmu."
"Tak mungkin." Jamie berbaring di kasur gulung, lalu melipat kedua lengannya rapat-rapat di dada.
Sekali lagi aku melihat membantah adalah pendekatan yang keliru untuk Jamie. Well, yang ini bisa langsung kuperbaiki setelah ia tidur. Jamie tidur sangat nyenyak, sampai nyaris bisa disebut koma. Melanie duku bisa menggendongnya ke mana pun setelah ia tertidur.
"Kau bisa memakai bantalku," kata Jamie kepadaku, seraya menepuk-nepuk bantal di sebelah tempatnya berbaring. "Kau tak perlu meringkuk di ujung sana."
Aku mendesah, tapi merangkak ke bagian atas tempat tidur.
"Nah, begitu," ujarnya setuju. "Sekarang, bisakah kau melemparkan bantal Jared kepadaku?"
Aku bimbang, hendak meraih bantal di bawah kepalaku. Jamie melompat bangun, membungkuk ke arahku, lalu meraih bantal yang lain. Aku kembali mendesah.
Sejenak kami berbaring dalam keheningan, mendengarkan siulan rendah napas Doc.
"Dengkuran Doc menyenangkan, bukan?" bisik Jamie.
"Tidak membuatmu terjaga," jawabku mengiyakan.
"Kau lelah?"
"Ya."
"Oh."
Aku menunggu Jamie mengatakan sesuatu lagi, tapi ia diam saja.
"Ada sesuatu yang kauinginkan?" tanyaku.
Jamie tidak langsung menjawab, tapi bisa kurasakan pergulatannya, jadi aku menunggu.
"Kalau aku menanyakan sesuatu, maukah kau mengatakan yang sebenarnya?"
Giliranku bimbang. "Aku tidak mengetahui semua hal," elakku.
"Yang ini kau pasti tahu. Ketika kami sedang berjalan... aku dan Jeb... dia menceritakan beberapa hal. Hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Tapi aku tak tahu apakah dia benar."
Mendadak melanie sangat hadir di dalam kepalaku.
Bisikan Jamie sulit didengar, lebih pelan daripada napasku. "Menurut Uncle Jeb, Melanie mungkin masih hidup. Maksudku, dia berada di dalam sana bersamamu."
Jamie-ku. Melanie mendesah.
Aku tak menjawab keduanya.
"Aku tak tahu apakah itu bisa terjadi. Apakah itu terjadi?" Suara Jamie pecah, dan aku bisa mendengar ia memerangi air mata. Ia bukan anak cengeng, dan aku kembali sangat sedih untuknya, dua kali dalam satu hari. Perasaan nyeri menembus dadaku.
"Benarkah, Wanda?"
Katakan kepadanya. Kumohon, katakan aku mencintainya.
"Kenapa kau tidak mau menjawabku?" Kini jamie benar-benar menangis, tapi ia mencoba meredam suaranya.
Aku merangkak turun dari tempat tidur, lalu menjejalkan diri ke celah keras di antara tempat tidur dan kasur gulung, mengulurkan tangan ke dada Jamie yang bergetar. Kusurukkan kepalaku ke rambutnya, dan kurasakan air matanya, hangat di leherku.
"Apakah Melanie masih hidup, Wanda? Kumohon?"
Mungkin Jamie hanyalah alat. Lelaki tua itu bisa saja mengutus Jamie khusus untuk ini; Jeb cukup pintar untuk melihat betapa mudah Jamie mematahkan pertahananku. Mungkin Jeb mencari penegasan atas teorinya, dan ia tak segan-segan menggunakan anak ini untuk mendapatkannya. Apa yang akan ia perbuat, ketika meyakini kebenaran berbahaya itu? Bagaimana ia akan menggunakan informasi itu? Kurasa ia tidak bermaksud jahat, tapi bisakah aku memercayai penilaianku sendiri? Manusia adalah mahluk penipu, pengkhianat. Aku tak bisa mengantisipasi niat mereka yang lebih kelam, karena hal-hal semacam itu tak terpikirkan oleh spesiesku.
Tubuh Jamie berguncang-guncang di sampingku.
Ia menderita, teriak Melanie. Sia-sia Melanie melawan kendaliku.
Tapi aku tak bisa menyalahkan Melanie, seandainya ini ternyata merupakan kesalahan besar. Aku tahu siapa yang kini sedang bicara.
"Melanie berjanji akan kembali, bukan?" gumamku. "Akankah dia mengingkari janjinya kepadamu?"
Jamie melingkarkan kedua tangannya di pinggangku dan menggayutiku untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit ia berbisik, "Aku sayang padamu, Mel."
"Dia sayang padamu juga. Dia sangat senang kau ada di sini dan aman."
Jamie diam cukup lama sehingga air mata di kulitku mengering, meninggalkan debu asin halus.
"Apakah semua orang seperti itu?" bisik Jamie, lama setelah aku mengira ia telah terlelap. "Apakah semua orang tetap tinggal di dalam sana?"
"Tidak," ujarku sedih. "Tidak. Melanie istimewa."
"Dia kuat dan berani."
"Sangat."
"Apakah menurutmu..." Jamie berhenti untuk menghela napas. "Apakah menurutmu Dad mungkin masih berada di sana juga?"
Aku menelan ludah, mencoba mendorong gumpalan itu lebih jauh ke dalam tenggorokan. Sia-sia. "Tidak, Jamie. Tidak, kurasa tidak. Tidak seperti Melanie."
"Kenapa?"
"Karena ayahmu membawa para Pencari untuk menangkapmu. Well, jiwa di dalamnya yang melakukan itu. Ayahmu takkan membiarkan itu terjadi, kalau saja dia masih di sana. Melanie tak pernah membiarkanku melihat di mana kabin itu berada. Dan untuk waktu yang lama sekali, dia bahkan tidak membiarkanku tahu kau ada. Dia tidak membawaku kemari, sampai merasa yakin aku takkan melukaimu."
Terlalu banyak informasi. Selesai bicara, baru kusadari Doc tak lagi mendengkur. Aku tidak bisa mendengar suara napasnya. Tolol. Diam-diam kumaki diriku sendiri.
"Wow," ujar Jamie.
Aku berbisik di telinganya, begitu dekat sehingga tak mungkin Doc bisa menguping. "Ya, Melanie sangat kuat."
Jamie berusaha keras mendengarku. Ia cemberut, lalu melirik lubang menuju lorong gelap. Ia menyadari hal yang sama, karena ia mengarahkan wajah ke telingaku dan kembali berbisik, lebih pelan daripada sebelumnya. "Mengapa kau bersedia melakukannya? Tidak melukai kami? Bukankah itu yang kauinginkan?"
"Tidak. Aku tidak ingin melukaimu."
"Mengapa?"
"Aku dan kakakmu telah... menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Dia membagimu untuk kami berdua. Dan... aku mulai... sayang padamu juga."
"Dan Jared juga?"
Sejenak aku menggertakkan gigi, merasa kesal karena dengan mudah Jamie bisa menghubungkan kedua hal itu. "Tentu saja aku juga tak menginginkan apa pun melukai Jared."
"Jared membencimu," ujar Jamie. Jelas ia sedih melihat kenyataan itu.
"Ya. Semua orang membenciku." Aku mendesah. "Aku tak bisa menyalahkan mereka."
"Jeb tidak membencimu. Aku juga."
"Kau mungkin akan membenciku, setelah lebih banyak merenungkannya."
"Tapi kau bahkan tidak berada di sini ketika mereka mengambil alih. Kau tidak memilih ayahku atau ibuku atau Melanie. Saat itu kau berada di luar angkasa, bukan?"
"Ya, tapi aku adalah aku, Jamie. Aku melakukan apa yang dilakukan jiwa. Aku punya banyak inang sebelum Melanie, dan tak ada yang menghentikanku untuk... merampas kehidupan. Berulang kali. Begitulah cara hidupku."
"Apakah Melanie membencimu?"
Sejenak aku berpikir. "Dia tidak terlalu membenciku seperti dulu."
Tidak. Aku sama sekali tidak membencimu. Tidak lagi.
"Katanya dia sama sekali tak membenciku," gumamku, nyaris tak terdengar.
"Bagaimana... bagaimana kabarnya?
"Dia senang berada di sini. Dia begitu bahagia berjumpa denganmu. Dia bahkan tak peduli apakah mereka hendak membunuh kami."
Jamie mengejang di bawah lenganku. "Mereka tidak bisa membunuhmu! Tidak bisa, jika Mel masih hidup!"
Kau membuatnya sedih, keluh Melanie. Kau tidak perlu berkata begitu.
Tidak bakal mudah baginya, kalau ia tidak siap.
"Mereka takkan percaya itu, Jamie," bisikku. "Mereka akan mengira aku berbohong untuk menipumu. Kalau kau menceritakan hal ini, mereka hanya akan semakin bernafsu membunuhku. Hanya Pencari yang berbohong."
Kata itu membuat Jamie bergidik.
"Tapi kau tidak bohong. Aku tahu itu," ujar Jamie setelah beberapa saat.
Aku mengangkat bahu.
"Aku takkan membiarkan mereka membunuh Mel."
Suara Jamie, walaupun sepelan napas, terdengar garang penuh tekad. Aku terpaku, membayangkan dirinya semakin terlibat dengan situasi ini, semakin terlibat denganku. Kubayangkan orang-orang barbar yang tinggal bersamanya. Apakah usia muda akan melindungi Jamie dari mereka, seandainya ia mencoba melindungiku? Aku ragu. Pikiranku campur aduk, mencari cara untuk mencegah Jamie tanpa memicu kekeraskepalaannya.
Jamie bicara sebelum aku bisa mengatakan sesuatu; mendadak ia berubah tenang, seolah jawabannya sudah jelas di depannya. "Jared akan memikirkan sesuatu. Dia selalu begitu."
"Jared juga tidak bakal percaya. Dia akan menjadi yang paling marah di antara mereka semua."
"Bahkan seandainya tidak percaya, dia akan melindungi Mel, sekadar berjaga-jaga."
"Akan kita lihat nanti," gumamku. Nanti akan kucari kata-kata yang sempurna--bantahan yang tidak akan terdengar seperti bantahan.
Jamie diam, berpikir. Akhirnya napasnya melambat dan mulutnya terbuka. Aku menunggu sampai yakin ia sudah tidur nyenyak, lalu aku menghampirinya, dan dengan sangat hati-hati memindahkannya dari lantai ke tempat tidur. Ia lebih berat daripada dulu, tapi aku berhasil. Ia tidak terbangun.
Kuletakkan bantal Jared di tempatnya, lalu kurebahkan tubuhku ke atas kasur gulung.
Well, pikirku. Aku baru saja mengeluarkan diriku dari wajah. Tapi aku kelewat lelah untuk memedulikan arti semua ini besok pagi. Dalam hitungan detik aku sudah tak sadarkan diri.
Ketika aku terbangun, semua celah di langit-langit kamar di terangi cahaya matahari yang menggema, dan seseorang sedang bersiul.
Siulan itu berhenti.
"Akhirnya," gumam Jeb, ketika mataku terbuka.
Aku berguling sehingga bisa memandangnya. Ketika aku bergerak, tangan Jamie menggelincir dari lenganku. Rupanya semalam ia mengulurkan tangan untuk menggapaiku. Well, bukan menggapaiku, tapi menggapai kakaknya.
Jeb bersandar di ambang pintu batu alami, tangannya terlipat di dada. "Pagi," sapanya. "Cukup tidurnya?"
Aku menggeliat, memutuskan merasa cukup istirahat, lalu mengangguk.
"Oh, jangan membisu lagi," keluh Jeb, memberengut.
"Maaf," gumamku. "Tidurku nyenyak. Terima kasih."
Jamie bergerak mendengar suaraku.
"Wanda?" tanya Jamie.
Dengan tololnya aku merasa terharu, karena ia mengucapkan nama panggilan tololku di pengujung tidurnya.
"Ya?"
Jamie mengerjapkan mata dan menyingkirkan rambut kusutnya.
"Oh, hei, Uncle Jeb."
"Kamarku tidak cukup baik untukmu, Nak?"
"Kau mendengkur sangat keras," ujar Jmaie. Lalu ia menguap.
"Belum pernahkah aku mengajarimu?" tanya Jeb kepadanya. "Sejak kapan kau membiarkan tamu perempuan tidur di lantai?"
Jamie mendadak duduk, menatap sekeliling, kehilangan orientasi. Ia memberengut.
"Jangan membuatnya khawatir," kataku kepada Jeb. "Dia berkeras tidur di kasur gulung. Aku memindahkannya ketika ia sudah terlelap."
Jamie mendengus. "Dulu Mel juga selalu begitu."
Aku sedikit memelototinya, mencoba mengingatkan.
Jeb tergelak. Aku mendongak memandangnya, dan ia memperlihatkan ekspresi kucing menerkam seperti kemarin. Seakan ia telah menemukan jawaban atas teka-tekinya Ia mendekat dan menendang ujung kasur.
"Kau sudah ketinggalan kelas pagimu. Sharon pasti marah soal itu. Ayo, bangun."
"Sharon selalu marah," keluh Jamie, tapi ia cepat-cepat bangkit berdiri.
"Cepat, Nak."
Jamie memandangku lagi, lalu berbalik dan menghilang ke dalam lorong.
"Nah," ujar Jeb, segera setelah kami sendirian. "Kurasa semua omong kosong tentang penjagan ini sudah berlangsung terlalu lama. Aku sibuk. Semua orang sibuk di sini--kelewat sibuk untuk duduk-duduk menjaga. Jadi hari ini kau harus ikut bersamaku, saat aku mengerjakan tugas-tugasku."
Mulutku menganga.
"Jangan kelihatan ketakutan begitu," gerutunya. "Kau akan baik-baik saja." Jeb menepuk-nepuk senapannya. "Rumahku bukan tempat untuk bayi."
Aku tak bisa membantah soal itu. Kuhela napas panjang cepat tiga kali, mencoba menenangkan saraf-sarafku. Darah berdenyut sangat kencang di telingaku, sehingga suara Jeb terdengar pelan ketika ia kembali bicara.
"Ayo, Wanda. Jangan menyia-nyiakan hari."
Jeb berbalik dan keluar dari kamar.
Sejenak aku terpaku, lalu terhuyung-huyung mengikutinya. Jeb tidak menggertak--ia sudah tidak terlihat lagi di belokan pertama. Aku bergegas mengejarnya, ngeri membayangkan akan berjumpa orang lain di bagian yang jelas tak berpenghuni ini. Aku menyusul Jeb sebelum ia tiba di persimpangan besar terowongan. Ia bahkan tidak memandangku, ketika aku memperlambat langkah di sampingnya untuk mengimbanginya.
"Sudah saatnya ladang timur laut ditanami. Kita harus menggarap tanahnya dulu. Kuharap kau tidak keberatan mengotori tanganmu. Setelah selesai akan kupastikan kau punya kesempatan untuk mandi. Kau membutuhkannya." Jeb sengaja mengendus-endus, lalu tertawa.
Kurasakan tengkukku memerah, tapi kuabaikan kalimat terakhir itu. "Aku tidak keberatan mengotori tanganku," gumamku. Ketika kuingat-ingat, ladang timur laut kosong itu terpencil letaknya. Mungkin kami bisa bekerja sendirian.
Setelah tiba di plaza utama, kami mulai melewati para manusia. Mereka menatap marah seperti biasa. Aku mulai mengenali sebagian besar. Ada perempuan setengah baya berambut hitam keabu-abuan panjang dikepang yang kulihat bersama tim irigasi kemarin. Lalu lelaki pendek berperut bulat, berambut pirang menipis dan berpipi kemerahan yang ada bersama perempuan tadi. Perempuan yang tampak atletis dengan kulit cokelat karamel adalah orang yang membungkuk mengikat tali sepatu ketika pertama kali aku kemari di siang hari. Perempuan berkulit gelap lain, dengan bibir tebal dan mata mengantuk, berada di dapur waktu itu, di dekat dua anak kecil berambut hitam. Mungkinkah perempuan itu ibu mereka? Kini kami melewati maggie. Ia memelototi Jeb dan memalingkan wajah dariku. Kami melewati lelaki pucat berambut putih yang tampak kurang sehat, yang pasti tak pernah kulihat sebelumnya. lalu kami melewati Ian.
"Hei, Jeb," sapa Ian ceria. "Mau ke mana?"
"Membalik tanah di ladang timur, gerutu Jeb.
"Perlu bantuan?"
"Harus membuat dirimu berguna," gumam Jeb.
Ian menganggap ini sebagai persetujuan, lalu mengikuti di belakangku. Aku merinding merasakan matanya memandang punggungku.
Kami melewati seorang pemuda, yang mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari Jamie, dengan rambut warna gelap mencuat dari kening warna zaitunnya, seperti wol baja.
"Hei, Wes," sapa Ian.
Wes mengamati ketika kami melewatinya. Ian tertawa melihat ekspresinya.
Kami melewati Doc.
"Hei, Doc," sapa Ian.
"Ian." Doc mengangguk. Di tangannya ada gumpalan besar adonan. Kemejanya dikotori tepung kasar warna gelap. "Pagi, Jeb. Pagi, Wanda."
"Pagi," jawab Jeb.
Aku mengangguk tidak nyaman.
"Sampai jumpa," ujar Doc, bergegas pergi membawa adonannya.
"Wanda, heh?" tanya Ian.
"Ideku," ujar Jeb. "Kurasa occok untuknya."
"Menarik." Hanya itu yang dikatakan Ian.
Akhirnya kami sampai di ladang timur laut, tempat harapan-harapanku hancur.
Lebih banyak orang di sini daripada di lorong-lorong. Lima perempuan dan sembilan laki-laki. Mereka berhenti bekerja dan, tentu saja, memberengut.
"Jangan pedulikan mereka," gumam Jeb.
Jeb mengikuti sarannya sendiri; ia pergi ke tumpukan peralatan yang tersandar di dinding terdekat, menyelipkan senapan ke pinggang, lalu meraih cangkul dan dua sekop.
Dengan jeb begitu jauh, aku merasa diriku jelas terlihat. Ian hanya selangkah di belakang. Bisa kudengar suara napasnya. Yang lain terus menatap marah, dengan peralatan di tangan masing-masing. Aku tidak melewatkan fakta bahwa cangkul yang digunakan untuk menghancurkan tanah bisa dengan mudah digunakan untuk menghancurkan tubuh. Saat membaca beberapa ekspresi mereka, bagiku tampaknya bukan hanya diriku yang punya gagasan semacam itu.
Jeb kembali dan memberiku sekop. Aku mencengkeram pegangan kayunya yang aus dan licin, merasakan bobotnya. Setelah melihat pandangan haus darah di mata manusia-manusia itu, sulit bagiku untuk tidak menganggap sekop itu senjata. Aku tidak menyukai gagasan itu. Aku ragu, apakah bisa mengangkat benda itu sebagai senjata, bahkan untuk menghalangi pukulan saja.
Jeb memberikan cangkulnya kepada Ian. Logam tajam menghitam itu tampak mematikan di tangannya. Perlu segenap tekad agar aku tidak menyelinap keluar dari jangkauannya.
"Ayo menggarap pojok belakang."
Setidaknya Jeb membawaku ke tempat yang paling tidak ramai di gua panjang terang itu. Ia menyuruh Ian menghancurkan tanah yang mengeras terpanggang matahari di depan kami, sementara aku menggemburkan bongkah-bongkah tanah itu. Jeb mengikuti di belakangku, dengan pinggiran sekop ia menghancurkan bongkahan-bongkahan itu menjadi tanah yang berguna.
Ketika melihat keringat yang mengaliri kulit putih Ian--ia melepaskan kemeja setelah beberapa detik terbakar cahaya cermin--dan mendengar napas tersengal-sengal Jeb di belakangku, kusadari aku mendapat pekerjaan termudah. Aku berharap diharuskan melakukan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang akan membuatku tidak terganggu oleh gerakan manusia-manusia lain. Setiap gerakan mereka membuatku tersentak dan menciut.
Aku tak bisa melakukkan pekerjaan Ian. Aku tidak punya lengan kekar dan otot-otot punggung yang dibutuhkan untuk benar-benar menghancurkan tanah keras. Tapi kuputuskan untuk melakukan pekerjaan Jeb sebisa mungkin. Kuhancurkan bongkahan-bongkahan itu sampai kecil-kecil sebelum bergerak maju. Pekerjaan itu sedikit membantu--membuat mataku sibuk dan sangat melelahkan sehingga aku harus berkonsentrasi untuk membuat diriku terus bekerja.
Sesekali Ian membawakan air. Ada perempuan--pendek putih, aku melihatnya di dapur kemarin--yang tampaknya bertugas membawakan air untuk yang lain. Tapi ia mengabaikan kami. Ian selalu membawa cukup air untuk kami bertiga. Aku cemas mellihat perubahan sikapnya mengenai diriku. Apakah Ian benar-benar tak lagi menginginkan kematianku? Ataukah ia hanya mencari kesempatan? Air selalu aneh rasanya di sini--apak dan bersulfur--tapi kini rasanya mencurigakan. Kucoba mengabaikan pikiran sinting itu sebisa mungkin.
Aku bekerja cukup keras untuk menyibukkan mata dan membekukan pikiran; aku tidak memperhatikan ketika kami tiba di ujung baris terakhir. Aku baru berhenti ketika Ian berhenti. Ia menggeliat, mengangkat cangkul ke atas kepala dengan dua tangan, lalu mengertakkan semua persendiaan tubuhnya. Aku menjauhi cangkul yang terangkat itu, tapi Ian tidak memperhatikan. Kusadari semua orang sudah berhenti bekerja. Aku memandang tanah yang baru saja digemburkan, bahkan memandang seluruh lantai, dan kusadari ladangnya sudah selesai digarap.
"Kerja kalian bagus," Jeb mengumumkan dengan suara lantang. "Kita akan menanam dan mengairinya besok."
Ruangan dipenuhi celotehan pelan dan bunyi berdentang ketika semua peralatan kembali ditumpuk menyandar di dinding. Beberapa percakapan terdengar santai; beberapa masih tegang karena kehadiranku. Ian mengulurkan tangan meminta sekopku, dan kuserahkan benda itu kepadanya, lalu kurasakan suasana hatiku ang lesu seakan tenggelam ke lantai. Tak diragukan lagi aku termasuk dalam kata "kita" yang diucapkan Jeb. Besok pasti sama sulitnya seperti hari ini.
Dengan sedih aku memandang Jeb, dan ia tersenyum. Ada perasaan bangga dalam seringai Jeb, yang membuatku percaya ia tahu apa yang kupikirkan. Ia tidak hanya menebak ketidaknyamananku, tapi juga menikmatinya.
Jeb, teman sintingku, mengedipkan sebelah mata. Kembali kusadari inilah hal terbaik yang bisa diharapkan dari persahabatan manusia.
"Sampai besok, Wanda," seru Ian dari seberang ruangan, lalu tertawa sendiri.
Semua menatapnya.














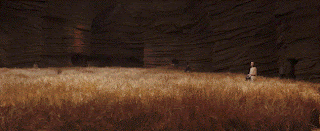













0 comments:
Post a Comment